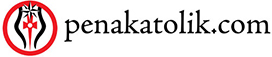(Renungan berdasarkan Bacaan Injil Minggu Kelima dalam Waktu Biasa [A], 9 Februari 2020: Matius 5: 13-16
Membaca dengan teliti, kita mungkin bertanya-tanya, “Apakah mungkin jika garam kehilangan rasa asinnya?” Dalam pengalaman sehari-hari, kita tidak pernah menemukan garam yang hambar. Namun, ketika kita kembali ke zaman Yesus, kita akan terkejut bahwa garam yang kehilangan rasanya adalah kenyataan sehari-hari. Di Israel kuno, orang-orang akan pergi ke Laut Mati, laut yang memiliki kadar garam paling tinggi di bumi, dan mengambil bongkahan-bongkahan garam yang terbentuk di sekitar danau. Kemudian, mereka akan dimasukkan ke dalam kantong kecil, seperti kantong teh, dan ketika dibutuhkan untuk bumbu, kantong itu akan dicelupkan ke dalam air atau sup. Setelah digunakan berulang-ulang, garam akan kehilangan rasa asinnya karena kandungan kimia yang tidak sempurna. Bongkahan garam pun berubah menjadi batu biasa, dan akan dibuang dan diinjak-injak.
Garam adalah bumbu yang sangat penting, tetapi karena jumlahnya sedikit, kita tidak menghiraukannya. Ketika saya masih di seminari menengah, salah satu pantang Prapaskah di seminari adalah makan makanan yang dimasak tanpa garam. Rasanya benar-benar ngak enak. Saya memaksakan diri untuk menelan makanan, tetapi itu hanya membuat saya merasa ingin muntah. Saya tidak pernah berpikir bahwa makanan tanpa garam hampir tidak bisa dimakan.
Bagi banyak dari kita, garam hanyalah bumbu yang biasa saja. Namun, bagi sebagian orang, garam berarti hidup dan mati. Dari waktu ke waktu, kita mengalami diare. Penyakit itu sendiri sebenarnya mudah diobati, tetapi jika tidak cepat ditangani, hal ini bisa mematikan karena menyebabkan orang mengalami dehidrasi parah. Salah satu cara tradisional untuk mengobatinya adalah “oralit” atau larutan rehidrasi oral. Ini adalah minum air dalam jumlah yang tepat dengan tambahan gula dan garam. Bagaimana garam kecil menyelamatkan nyawa orang!
Namun, kita perlu mengingat bahwa garam adalah bumbu dan bukan menu utama. Seseorang tidak dapat bertahan hidup hanya dengan garam saja. Terlalu banyak garam dalam tubuh kita akan menyebabkan tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal bagi banyak organ tubuh kita. Yesus menyebut kita “garam” karena kita dipanggil untuk memberikan citarasa yang pas pada sang Roti Kehidupan. Ketika saya masih belajar di Manila, saya diperkenalkan dengan salah satu sarapan favorit orang Filipina, “pan de sal.” Ini adalah bahasa Spanyol untuk “roti garam” karena sedikit garam ditambahkan ke tahap akhir pembuatan adonan roti ini. Bentuk rotinya sederhana, namun enak dan gurih, dan membuat orang ketagihan.
Seperti garam di Pan de Sal, misi kita sebagai umat Kristiani adalah membawa Yesus kepada orang lain dan menjadikan orang lebih merindukan Yesus. Ini adalah pekerjaan yang sulit karena hidup dan tindakan kita harus pas, tidak terlalu asin, dan tidak hambar. Semakin kita menarik perhatian pada diri kita sendiri, semakin banyak orang akan merasa “terlalu asin.” Namun, tanpa melakukan upaya kita, Kristus akan tampak “hambar.”
Setiap kali kita pergi ke Misa, kita menerima Tubuh Kristus dalam bentuk roti putih, kecil, dan tanpa rasa, sebuah hosti. Mengapa tidak berasa? Karena saat kita pulang, kita perlu menjadi rasa bagi Roti hidup ini. Jadi, bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita (lihat Gal 2:20).
Pastor Valentinus Bayuhadi Ruseno OP