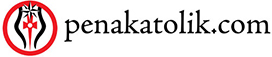Sebagai seorang pemuda usia sekolah menengah di Seoul, Korea Selatan, Min Seo Park belajar seni di sekolah teknik untuk tunarungu. Dia kehilangan pendengaran sepenuhnya pada usia 2 tahun, akibat pengobatan untuk penyakit serius.
Kemampuan artistiknya bukanlah yang terbaik, maka dia ikuti les privat bidang desain. Setelah beberapa saat, tutor yang juga tunarungu mengenalkan kepadanya iman Katolik. Park berasal dari keluarga Buddha, tetapi senang pergi ke gereja Kristen bersama para siswa tunarungu lainnya. Membaca buku yang diberikan gurunya, dia menemukan sesuatu yang baru dan memberi energi dalam agama Katolik.
Dan dia bisa menghadiri Misa di sebuah gereja Katolik yang punya penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu. Tetapi imam, yang tidak tuli, itu berkhotbah dalam bahasa yang, kenangnya, melampaui kepala sebagian besar umatnya. Beberapa umat tunarungu yang hadir tertidur selama homili, kenang Park.
“Yang lain frustrasi dan baru saja akan pergi, dan saya bertanya kepada mereka ‘Mau pergi ke mana?’ Mereka berkata ‘Kami mau ke gereja Protestan,’ karena pendeta itu [yang tuli] jelas dan mudah dimengerti, dan mereka tidak mau punya imam yang bisa mendengar dengan penerjemah. Itu semua membingungkan dan mereka merasa sangat bosan.”
Meskipun Park telah dibaptis, imannya “belum benar-benar berakar,” katanya, dan dia tergoda untuk kembali ke gereja Protestan. Di sana, homili pendeta disampaikan dalam bahasa isyarat yang “jelas dan indah.”
“Maka saya berdoa dan minta kepada Allah untuk mengirim saya seorang imam yang tahu bagaimana membantu orang tuli,” katanya. “Saya tidak dapat tanggapan. Saya terus berdoa, tetapi saya merasakan perasaan bahwa Yesus berkata kepada saya, ‘Baiklah, mengapa bukan engkau?’ Saya berpikir, ‘Saya? Bagaimana seorang tunarungu bisa jadi imam? Itu tidak mungkin.’ Tetapi perasaan itu benar-benar mulai tumbuh dalam diri saya, bahwa saya dipanggil untuk memenuhi kebutuhan itu. Begitulah panggilan saya benar-benar dimulai.”
Sekarang di usia 52 tahun, Pastor Min Seo Park telah menjadi imam Keuskupan Agung Seoul selama 14 tahun, dan sebagian besar melayani di Paroki Ephatha untuk umat Katolik tunarungu di Seoul. Dia baru-baru ini memulai tugas tiga tahun sebagai kapelan “pinjaman” untuk Gereja Katolik Tuna Rungu Santo Fransiskus dari Assisi di Keuskupan Agung Washington, DC, dan kapelan Katolik di Universitas Gallaudet, universitas yang disewa secara federal untuk orang tuli dan sulit mendengar di ibu kota negara itu.
Dia berbicara dengan Aleteia dalam wawancara Zoom, dengan terjemahan oleh Mary O’Meara, Direktur Eksekutif Departemen Pelayanan Khusus untuk Keuskupan Agung Washington.
Jalan Pastor Park menuju imamat penuh lubang, polisi tidur, dan jalan memutar. Jalan itu dimulai saat dia mempelajari tentang seorang imam Amerika yang tuli, Pastor Tom Coughlin. “Sejak itu saya sadar, ‘ada kemungkinan menjadi imam yang tuli.’ Itu memberi saya harapan.” Pastor Coughlin, yang ditahbiskan imam tahun 1977 di Baltimore, adalah imam tunarungu pertama di Amerika Utara. Dia mendirikan Misionaris Dominikan untuk Kerasulan Tuli dan terus aktif.
Pastor Coughlin dorong Park datang ke Amerika Serikat dan belajar di Gallaudet seperti yang dia lakukan, dan belajar bahasa isyarat Inggris dan Amerika dan mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat. Dari sana, Park memasuki program untuk para frater tunarungu yang dibentuk Pastor Coughlin di Keuskupan Agung New York. Di Seminari Santo Yosef di Yonkers, N.Y., siswa pertukaran muda itu belajar bersama sekitar 20 frater yang bisa mendengar.
“Wah, itu tantangan besar buat saya,” kenangnya. “Latar belakang dan kredensial akademis mereka jauh lebih kuat dari saya. Saya harus sangat sabar. Para guru berbicara sangat cepat. Saya tak punya juru bahasa, hanya laptop dengan seseorang yang mengetik untuk saya. Karena profesor berbicara begitu cepat, sangat tak mungkin mengetik semua, dan saya kehilangan banyak hal. … Saya benar-benar tidak memahami segalanya, dan saya tertinggal jauh.”
Setelah sekitar satu tahun, nilainya biasa-biasa saja. Dia menerima surat dari pejabat seminari yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat meramalkan kemungkinan dia menjadi imam. “Mereka pikir yang terbaik adalah saya tinggalkan seminari,” katanya. “Pada saat yang sama program untuk para frater tunarungu ditutup. Itu sangat mengejutkan. Saya sungguh sedih. Saya tak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya.”
Pastor Coughlin mendorongnya untuk tidak menyerah. Dia menunggu dan berdoa, dan suatu hari mengambil buku secara acak dan mulai membaca. Itu tentang Santo Yohanes Vianney, yang juga diminta meninggalkan seminari, karena keterampilan bahasa Latinnya buruk. Tetapi Pastor Vianney mengajukan petisi kepada uskup dan mendapat bantuan ekstra untuk seminaris muda itu. Vianney tidak hanya ditahbiskan, dia ternyata seorang imam teladan sehingga sekarang dia dianggap sebagai santo pelindung para pastor paroki.
“Saya merasa kami berada dalam situasi sama dan bahwa dia bertahan dan benar-benar menjadi imam,” kata Pastor Park. “Saya merasa positif lagi dan saya percaya bahwa Tuhan akan menanggapi.”
Pastor Coughlin membantu Park mengikuti program di Universitas Santo Yohans di Queens, New York. Di sana, frater muda itu dibantu oleh dua penerjemah dan seorang pencatat. Park memperoleh gelar Master di bidang keilahian tahun 2004 dan pulang ke Seoul untuk ditahbiskan.
Sebagai pastor Efatha di Seoul, Pastor Park merayakan Misa dalam Bahasa Isyarat Korea untuk sekitar 200-250 orang setiap hari Minggu. Bagian dari pekerjaannya adalah membangun gereja, yang selesai pada Agustus 2019.
Tetapi komunitas Washington kekurangan imam, dan Mary O’Meara “mencari ke mana-mana untuk mendapatkan seorang imam yang mendengar dan bisa memberi tanda dan ada imam-imam sebagai penerjemah,” kata Pastor Park. “Mary minta saya datang dan melayani umat.”
Seperti yang lain, umat di Paroki Santo Fransiskus tunduk pada pembatasan Covid, dan akhir-akhir ini, hanya sekitar 30 orang yang hadiri Misa secara langsung di hari Minggu. Misa disiarkan langsung secara online.
O’Meara mengatakan, meskipun sekitar 9% orang Amerika “sangat tuli” dan menggunakan bahasa isyarat, ada konsentrasi lebih besar di Washington, karena lulusan Gallaudet cenderung tetap tinggal di tempat lokal, “untuk rasa komunitas” dan untuk pekerjaan serta peluang lainnya.
Gallaudet saat ini ditutup karena pandemi, tetapi Pastor Park mengatakan kampus harus memiliki kapasitas 50% selama musim panas dan terbuka penuh di musim gugur. Dia berharap bisa bekerja bersama para mahasiswa di sana, dia pernah menjadi salah satunya. Dia akan bisa memberikan kepada mereka jenis dorongan yang dia terima dari orang lain ketika keadaan tampak begitu suram.(PEN@ Katolik/paul c pati/John Burger/Aleteia)