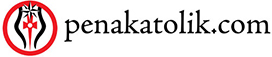Pastor Firas Lufti adalah seorang Fransiskan yang bekerja di Tanah Suci. Dia adalah Minister OFM Wilayah Santo Paulus yang meliputi Suriah, Libanon, dan Yordania. Dalam kisah ini, imam itu menggambarkan sembilan tahun kekerasan, kehancuran dan kematian selama perang di Suriah dan bagaimana dia tinggal di sana bersama umatnya, dan bagaimana dia kini membantu anak-anak untuk menemukan kembali senyum mereka. Kisah yang ditulis oleh Silvonei Protz untuk Vatican News ini diterjemahkan oleh Paul C Pati dari PEN@ Katolik untuk Anda:
Jika mengandalkan apa yang dilihat dan dibaca di media, mungkin Anda mengira perang di Suriah sudah berakhir. Itu karena hanya sedikit media membicarakannya lagi. Sebagai orang Suriah yang tinggal di Suriah, perang itu sangat meresahkan bagi Pastor Firas Lufti OFM, yang tinggal di negaranya sepanjang perang itu. “Memang benar pertempuran telah berhenti di beberapa daerah,” kata imam itu, “tetapi kita harus memperhitungkan fakta bahwa perang itu berlangsung sembilan tahun. Telah terjadi kehancuran besar-besaran, rumah-rumah hancur, seluruh daerah penuh reruntuhan, gereja-gereja harus dibangun kembali … Setengah dari jumlah penduduk sebesar 23 juta sebelum perang sudah tidak ada, ada yang meninggal, ada yang mengungsi dan ada yang pindah.”
Sebagai Fransiskan dan Katolik, Pastor Firas tidak pernah menyerah. Meskipun ada saat-saat sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, hati Fransiskannya terus mencari solusi. “Bagaimana bisa membantu umat saya?” terus-menerus imam itu bertanya pada dirinya. Sudah banyak yang dilakukan Komunitas Fransiskan internasional. Dengan bantuan kampanye solidaritas dan kemurahan hati dari banyak dermawan, imam itu mampu membagikan paket makanan dan air minum. Sumbangan membuat imam itu bisa membiayai proyek mikro, atau membantu pasangan muda yang sudah menikah. “Proyek-proyek adalah kesaksian bahwa Tuhan memberi dan terus memberi,” kata imam itu.
Di tengah tragedi perang, Pastor Firas mengatakan ia terus merasakan kehadiran Allah yang sangat konkret. Imam itu menegaskan, Gereja tidak pernah mengesampingkan orang-orang menderita. Tekanan perang memaksa beberapa imam dan kaum religius pergi, kata imam itu, tetapi mayoritas uskup, imam dan ordo religius memutuskan tetap tinggal. Dia memberi contoh dua teman Fransiskan yang tinggal di utara negara itu, dekat perbatasan dengan Turki, dekat dengan kota bersejarah Antiokhia. “Mereka tinggal di sana di bawah kendali kaum jihadis,” katanya, “sambil memperhatikan kelompok kecil umat Katolik yang tetap tinggal.” Ada sekitar 200 umat Katolik di daerah itu. Mereka tidak hanya membawa agamanya dalam DNA, tetapi juga menderita guna mempertahankan kesaksian konkret 2000 tahun kehadiran Kristen di sana, tempat orang Kristen pertama kali mengadopsi nama “pengikut Kristus.”
Ada dua proyek untuk anak-anak yang kini sedang berlangsung di Suriah. Salah satunya di kota Aleppo, tempat Pastor Firas tinggal selama perang. Nama proyek itu “seni terapi.” Tim spesialis dan para sukarelawan melakukan apa saja untuk bisa membantu anak-anak pulih dari trauma psikologis akibat perang. Kegiatan-kegiatannya antara lain musik, olahraga, dan berenang. “Kami sediakan kolam renang yang indah karena selama perang mereka tidak bisa bermain, meninggalkan rumah, atau belajar, karena takut terbunuh,” kata Pastor Firas. Sekitar seribu anak datang ke pusat itu selama musim panas.
Proyek lain melibatkan umat Muslim. “Hanya umat Muslim yang hidup, dan masih hidup, di Aleppo Timur,” jelas Pastor Firas. “Selama perang, tanah mereka diduduki para jihadis. Perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh … Anak-anak menyaksikan adegan mengerikan pemotongan leher oleh orang-orang fanatik ini.” Imam itu menggambarkan pernikahan paksa jihadis dengan wanita-wanita Suriah, dan anak-anak lahir dari perkawinan itu. Anak-anak itu tidak diakui secara resmi. Tidak ada pendaftaran kelahiran mereka di kantor pendaftaran. Mereka ada secara fisik, tetapi tidak secara hukum. Ketika para jihadis meninggalkan Aleppo tahun 2017, situasinya mengerikan, kata Pastor Firas. “Anak-anak berusia 4 atau 5 tahun tinggal bersama ibu atau nenek mereka karena orang tua mereka tidak ada lagi. Beberapa dibiarkan begitu saja dan tidak sekolah. Belum lagi trauma psikologis dan akumulasi teror yang mereka alami selama pertempuran.”
Ada dua pusat, masing-masing menampung 500 anak laki-laki dan perempuan mulai dari usia 3 atau 4 tahun, hingga 16. Program lain, yang sudah ada di kolese “Terre Sainte” Aleppo, diperpanjang. Pastor Firas menekankan kedua pusat itu lahir dari hubungan dengan dunia Muslim. “Mufti dari Aleppo adalah sahabat yang sangat kami sayangi,” jelas imam itu, “dan bersama-sama Vikaris Apostolik dari komunitas Latin dari Suriah tumbuh persahabatan, sebelum dan selama perang.” Buah pertama adalah kolaborasi yang lebih akrab guna mengatasi kebutuhan mendesak anak-anak yang trauma oleh perang.
Proyek itu dijalankan dalam kerja sama erat dengan umat Muslim dan memiliki makna mendalam bagi Pastor Firas. Proyek itu menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, untuk menyebarkan harapan, dan untuk menyembuhkan luka. Menurut Pastor Firas, dialog bukanlah apa yang dilakukan di sekitar meja, tetapi “bekerja bersama, bergandengan tangan, dari hati ke hati.” Mungkin butuh 30 bahkan 50 tahun untuk membangun kembali Suriah, kata imam itu, tetapi rekonstruksi sejati datang dari dalam: bukan dengan batu bata, tetapi dengan membangun kembali pribadi di dalam kita.
Kalau ada yang bertanya kepada Pastor Firas mengapa dia tinggal di Suriah selama perang, jawabannya selalu sama, “Karena saya seorang Fransiskan, seorang beriman. Dan kalau Tuhan menciptakan saya di sana, itu untuk suatu tujuan: menjadi wajah-Nya, tangan-Nya, kaki-Nya yang membawa Kabar Gembira, kelembutan, dan belas kasih Allah.”
Pastor Firas merasa dia “dipanggil” oleh Allah untuk membagikan pengalaman dramatis negaranya, tempat orang menderita dan mati setiap hari. “Sama seperti sebutir gandum yang harus mati guna menghasilkan banyak buah,” simpul imam itu. “Persis seperti yang Yesus katakan dalam Injil.”***