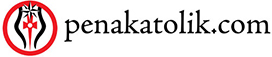Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) IV Tahun 2015 sudah berakhir. Seorang peserta, Pastor Albertus Sujoko MSC, seorang doktor teologi dari Universitas Alfonsiana di Roma, menulis pengalamannya mengikuti SAGKI. Pengalaman dari mantan Ketua STF Seminari Pineleng (2003-2011) dan sekarang Ketua Program Imamat untuk para frater MSC tingkat V dan VI Seminari Hati Kudus Pineleng, Sulawesi Utara itu, dikirim juga ke PEN@ Katolik yang kemudian mengangkatnya:
Beberapa tahun lalu di wilayah Gereja di Asia disebutkan bahwa Komunitas Basis adalah a new way of being Church (cara baru menggereja). Gereja institusional dan triumphalistis digantikan dengan Gereja yang merakyat dan mengumat. Cara menggereja di Indonesia, menurut saya, sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau saya bandingan dengan cara menggereja di paroki-paroki Italia, sejauh saya pernah mengalaminya.
Saya pernah membantu tugas Natal dan Paskah di paroki yang terletak di daerah Firenze (Florance) dan Olegio, dan pernah tinggal sebulan di Paroki MSC di Palermo di Pulau Sicilia. Di Firenze itu, pastor parokinya sudah 40 tahun menjadi pastor di situ dan tidak pernah pindah dan tidak akan pindah sampai mati. Rupanya memang seperti itu penempatan seorang pastor paroki untuk imam diosesan, yaitu bersifat tetap. Kalau imam tarekat religius akan dipindah-pindah oleh tarekatnya.
Kitab Hukum Kanonik, kanon 522, menyebutkan bahwa “pastor paroki bersifat tetap dan diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan”. Namun di Gereja Asia dan Indonesia, hal itu tidak mungkin terjadi. Baik imam diosesan maupun tarekat akan dipindahkan setelah beberapa tahun menjadi pastor paroki.
Cara baru menggereja di wilayah misi ditandai oleh peranan awam yang sangat besar. Awam sangat terlibat dalam setiap tingkatan Gerejani mulai dari KWI, keuskupan sampai paroki, bahkan wilayah rohani atau lingkungan. Penyelenggaran SAGKI itu pun terselenggara dengan baik karena kepandaian umat awam untuk memikirkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan itu. Para uskup dan imam praktis hanya mengikuti saja apa yang sudah disusun oleh para awam yang berpengalaman menyelenggarakan event-event besar.
SAGKI baru mulai tahun 2000 dan para uskup memutuskan untuk menyelenggarakan SAGKI itu satu kali setiap 5 tahun. Maka SAGKI 2015 ini adalah SAGKI IV. Ide untuk menyelenggarakan pertemuan perwakilan umat Katolik se-Indonesia itu mungkin juga didorong oleh kenyataan keterlibatan umat dalam menggereja. Setelah SAGKI selesai, para uskup melanjutkan Sidang KWI biasa.
Saya bersyukur dan beruntung dipilih oleh Uskup Manado untuk ikut SAGKI 2015, karena peristiwa yang berlangsung, perjumpaan-perjumpaan yang terjadi, proses, dan pengalaman kebersamaan di meja makan, dalam sharing kelompok, pertemuan di gang dan taman, dan doa bersama dalam ibadat harian dan Ekaristi adalah pengalaman hidup menggereja yang sesungguhnya.
Dokumen SAGKI tidak banyak gunanya. Pertama, mungkin tidak akan dibaca. Kedua, kalau dibaca mungkin tidak dimengerti. Ketiga, kalau dibaca dan dimengerti, mungkin mengecewakan: mengapa cuma seperti itu, tidak menggigit dan revolusioner. Keempat, kalau sudah dimengerti dan mengecewakan, akan ditafsirkan sesuai dengan pikiran pembaca sendiri.
Jadi saya pesimis bahwa hasil Keputusan SAGKI itu ada gunanya, meskipun uang yang dikeluarkan untuk mengumpulkan 569 orang dari 37 keuskupan se-Indonesia dengan 37 uskup dan 80 pastor, tidak terhitung suster dan awam, pastilah sangat besar.
Biaya dari Manado untuk setiap orang sekitar 3 juta rupiah. Dari Papua mungkin lebih mahal. Belum lagi biaya makan-minum dan sewa tempat sejak Senin hingga Jumat di Via Renata, Cimacan, Jawa Barat itu. Belum lagi biaya alat tulis dan tas-tas SAGKI untuk tiap peserta, serta kaos-kaos dan baju-baju seragam yang diusahakan oleh setiap kelompok peserta. Sebelum pulang ke daerah, sebagian ibu-ibu masih juga ke Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang. Pokoknya pasti besar sekali belanja barang dan jasa selama SAGKI, yang hasilnya juga masih perlu disosialisasikan itu.
Padahal hasil keputusan SAGKI, yang hanya terdiri dari 17 paragraf dalam 4 halaman dan ditanda-tangani oleh semua uskup (saya senang bisa melihat tanda tangan para uskup termasuk yang paling acak-acakan dari uskup Surabaya dan uskup Purwokerto, he he he), dikerjakan dengan susah payah.
Team Perumus harus mencantumkan pokok gagasan yang muncul dalam sidang-sidang pleno, tidak boleh karang-karang sendiri. Maka waktu draft pertama dibacakan pada hari Kamis sore oleh Uskup Bandung Mgr Antonius Subianto Benjamin OSC, yang paling muda dan paling ganteng, langsung mendapatkan kritik habis-habisan dari forum, terlebih dari para uskup.
Maka team perumus memperbaikinya dengan memasukkan usulan-usulan itu dan disebarkan kepada para uskup pada hari Kamis malam. Para uskup membacanya dan memberikan koreksi-koreksi lagi. Pada hari Jumat dini hari, team perumus menyusun draft ketiga untuk diserahkan kepada para uskup yang membacanya dengan teliti sebelum membubuhkan tanda tangan.
Team perumus yang antara lain terdiri dari para uskup baru dan muda, Uskup Bandung dan Uskup Bogor, sepertinya benar-benar tidak tidur. Maka ketika di akhir Misa Penutupan hari jumat siang, Uskup Bandung membacakan hasil final dari draft ketiga itu, beliau kentara sekali menahan rasa mengantuk dan lelah sehingga satu dua kata salah baca. Maka, kalau Anda menghargai jerih payah mereka itu, paling tidak: bacalah!
Kesan Pribadi
Panitia merencanakan kegiatan dengan sangat cermat, sehingga kegiatan mengalir dan menghindari pemborosan waktu yang tidak perlu. Misalnya pembagian kelompok. Kalau hal itu dilakukan ketika peserta sudah berkumpul, pasti tidak mungkin bisa cepat membagi orang sebanyak ke dalam kelompok.
Dalam buku panduan acara sudah dibagi 17 kelompok dan tidak ada satupun orang dari keuskupan yang sama berada dalam kelompok yang sama. Semua sudah diacak dan diusahakan terdiri dari semua keuskupan. Setiap kelompok yang umumnya terdiri dari 25 orang, memiliki anggota uskup, suster, pastor atau bruder dan awam.
Saya berada dalam kelompok 11 yang terdiri dari 25 orang. Di kelompok saya ada seorang ibu dari Keuskupan Agats Asmat, Papua, beranama Walburga Yewbap yang mempunyai delapan anak. Ibu itu kecil dan kurus tetapi kuat, dia harus bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya. Suaminya tidak tahu bekerja dan tidak bertanggungjawab untuk bisa membesarkan anak-anak. Syukurlah ada bantuan dari para suster, sehingga anak-anak bisa sekolah bahkan ada yang kuliah.
Dalam kelompok saya ada Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo dan Uskup Agung Makassar Mgr John Liku Ada. Saya tidak tahu entah karena apa, mereka memilih saya untuk menjadi moderator dalam diskusi kelompok itu. Selesai hari pertama, saya mengusulkan supaya tiap hari moderator diganti. Tetapi mereka bilang, tidak perlu ganti-ganti, satu orang saja sampai selesai.
Yang menjadi sangat terkenal adalah Kelompok 8. Karena dalam kelompok itu ada seorang ibu dari Papua, utusan Keuskupan Sorong. Nama itu itu Marcela Inanosa. Dalam sesi tanya jawab di forum besar itu, ibu itu mengangkat tangan dan kebetulan moderator melihatnya dan memberi kesempatan. Dengan sangat lantang ia bertanya kepada panitia SAGKI, “Mengapa dari keluarga-keluarga yang diminta sharing oleh Panitia itu tidak ada satu pun keluarga dari Papua? Mengapa seolah-olah dari Papua dipinggirkan dan kurang diperhatikan?”
Semua kaget dan sadar akan kenyataan bahwa memang tidak ada keluarga dari asli Papua yang diminta untuk sharing. Memang hanya delapan keluarga yang dipilih dan tentu banyak keuskupan lain juga tidak terwakili, termasuk tidak ada dari Manado. Namun bahwa tidak ada satupun perwakilan dari keluarga Papua untuk sharing di depan forum SAGKI itu membuat protes Marcela terasa kuat menggema. Maka ketika ia dipercaya oleh kelompoknya untuk tampil membacakan hasil diskusi dari kelompok 8, ia harus mengatakan: “Saya tampil mewakili kelompok 8, bukan kelompok Papua.” Dan semua orang tertawa.
Namun dalam Misa Penutup, Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM menceriterakan penghayatan hidup kepala suku Papua dan masyarakatnya yang sangat spiritual menurut caranya. Intinya, kepala suku itu mengatakan, “Bapak Uskup, saya ini Katolik, meskipun saya belum dibaptis. Ada Yesus di rumah saya. Batu panjang dan tas noken itu adalah Yesus.
Waktu Uskup Leo Laba baru memasuki kompleks rumah kepala suku itu, ia menyambut dengan sangat hormat karena tahu yang datang adalah pemimpin Gereja Katolik. Kepala suku itu hanya mengatakan saku kata diulang-ulang: “Wah…wah…wah…!” Tidak ada kata lain. Kata itu sudah mengungkapkan semuanya!
Uskup Leo Laba mengatakan, “Umat katolik saya hanya 82 ribu orang, tetapi menurut catatan pemerintah, umat Katolik di keuskupan saya ada 300 ribu orang, karena yang lainnya itu adalah Katolik yang belum dibaptis.”
Khotbah Uskup Leo panjang dan sangat mengesan. Beliau hanya menceriterakan pengalamannya berjumpa dengan spiritualitas atau penghayatan hidup orang Papua. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang Papua memberi makna-makna terhadap kehidupan dan benda-benda dan masyarakatnya.
Yang saya tidak mengerti Mgr Leo beberapa saat terdiam dan seperti mau menangis terharu ketika membayangkan kepala suku itu juga menangis terharu waktu bertemu dengan uskup dan menjelaskan pengalaman hidupnya. Pertanyaan saya, “Pengalaman seperti apa yang membuat uskup juga terdiam dan terharu dalam khotbah itu?”
Saya akhiri cerita saya ini dengan ungkapan hati dari Monica Ngantung dari Paroki Tataaran, Keuskupan Manado, salah satu utusan Mudika dari Keuskupan Manado. Sepertinya hanya dia yang Mudika, karena keuskupan lain tidak mengutus Mudika. Kebetulan Monica berparas cantik dengan kulit putih bersih sehingga menarik perhatian. Dialah yang paling ngetop dari kelompok Manado dan dia juga yang diwawancarai TV SAGKI.
Dia mengatakan empat hal yang sangat berkesan. Pertama, sharing kelompok yang sangat memperkaya. Kedua, bisa memotret semua wajah uskup dari seluruh Nusantara. Ketiga, animasi kegiatan untuk selingan, menyanyi dan menari dengan para uskup dan imam dan suster dan umat itu sangat menyenangkan. Keempat, testimoni-testimoni keluarga yang sungguh mengharukan dan memperkaya. “Mungkin pertemuan ini hanya akan terjadi sekali seumur hidup saya,” kata Monika.***