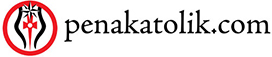Catatan dari AM Putut Prabantoro*
Berita meninggalnya Pastor Ignatius Sumarya SJ pada Minggu 27 Oktober 2013, saya baca pukul 08.30 di hari yang sama dengan tidak yakin. Seperti Thomas yang tidak mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit dari wafat, seperti itulah kira-kira gambaran ketidakyakinan saya bahwa Rektor Seminari Menengah Petrus Kanisius Mertoyudan, Magelang, itu meninggal dunia.
Sehari sebelumnya, saya bertemu Romo Maryo, demikian panggilan akrabnya, dalam makan malam yang sudah direncanakan. Sembilan orang hadir di meja perjamuan itu termasuk Pastor Eka Heru Nurcahyana SJ dan empat siswa seminari, Benediktus Juliar Elmiawan dari Bandung, Carolus Boromeus Aditya Deddy Perdana dari Ganjuran, Yogyakarta, Gregorius Dimas Arya Pradipta dari Pugeran, Yogyakarta, dan Yohanes Bernevo Puchrima Wardana dari Klaten. Kami semua tidak pernah menyangka bahwa saat itu adalah The Last Supper atau Perjamuan Terakhir kami bersama Romo Maryo.
Di stall makanan Seafood 99, Salsa Gading Serpong, kami memesan dua ekor ikan gurame asam pedas, satu fu yung hai, dua piring pare ikan asin, dua hotplate kangkung belacan, dan satu mangkuk mun tahu serta masing-masing satu porsi nasi. Ini bukan makanan mewah tapi makanan lezat yang jarang ditemui di Seminari Menengah Mertoyudan, yang merupakan tempat kelahiran PTIK dan Akademi Polisi Indonesia tahun 1946.
Sambil melayani keempat siswanya, pastor berusia 60 tahun itu meminta mereka makan sayur, gizi tinggi bagi pertumbuhan. Anak-anak jaman sekarang enggan makan sayur dan lebih menyukai junkfood. Romo Maryo menasehati, sayur yang dihidangkan adalah gizi sempurna untuk bekal marathon esok hari.
Mereka berenam, demikian penuturan Romo Maryo, datang ke Jakarta dari Mertoyudan untuk memenuhi undangan lomba dari Mandiri Jakarta Marathon dan sekaligus sebagai tanda hormat kepada kelompok eks Siswa Canisius College, Menteng, Jakarta.
Romo Maryo akan ikut lomba marathon 5 kilometer dan para siswa seminari akan ikut marathon 10 kilometer. Mengingat usia sudah kepala enam, keraguan akan kekuatan berlari ditepis oleh Romo Maryo dengan mengatakan, “kita ini penggembira dan bukan hadiah sebagai tujuan.” Selain itu, menurut analisa Romo Maryo, dengan 10.000 peserta tentu tidak mungkin peserta dapat lari dengan cepat.
“Ini adalah peristiwa bersejarah. Untuk pertama kalinya Jakarta mengadakan marathon, dan kebetulan saya ikut dalam marathon itu. Oleh karena itu, saya minta teman-teman meliput saya yang sedang lari. Yang berlari adalah seminari Mertoyudan….,” pinta Romo Maryo di meja perjamuan itu.
Menanggapi usulan itu, saya mengusulkan agar empat seminaris itu “dicukur gundul agar menarik perhatian dan berlari sambil membawa spanduk Seminari Mertoyudan.” Ah … usulan itu, sekalipun didukung oleh Romo Maryo, ditolak halus para siswa seminari sambil tertawa dan mengelus rambut-rambut mereka yang lebat.
Di perjamuan makan, Romo Maryo terkenang akan kehadiran Basuki Tahja Purnama (Ahok) di Seminari Mertoyudan, Juli 2011. Waktu itu, Ahok, yang masih anggota DPR dan berhasrat mengikuti pencalonan Gubernur DKI, hadir sebagai pembicara dalam seminar pluralisme bersama Ketua Masyarakat Islam Moderat Zuhairi Misrawi, Wakil Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Teguh Santosa, Wapemred Kompas Trias Kuncahyono dan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta Maryatmo sebagai moderator.
Menurut kacamata Romo Maryo, gaya kepemimpinan dwitunggal Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok akan mempengaruhi begitu banyak gubernur, walikota dan bupati dalam mengelola daerahnya. Harapannya, Indonesia segera mengalami perubahan dan kemajuan dalam mengelola negara yang makin amburadul.
“Inilah adalah sejarah pertama Jakarta menjadi tempat marathon dan saya ikut di dalamnya. Jika banyak pemimpin daerah menggunakan pendekatan budaya seperti ini, konflik horizontal pasti akan berkurang karena interaksi ini membuat orang kenal satu sama lain,” ujar Romo Maryo.
Diskusi ringan dan berat senantiasa diselingi canda tawa serta kesan tak henti-hentinya betapa “nikmatnya” makan di malam itu. Memang tidak seperti biasa, Romo Maryo yang terkenal “kaku” dan sedikit bicara, malam itu seakan kelebihan dosis. Tidak tahu, apakah kelebihan dosis bicara itu ada hubungannya dengan minuman es susu soda gembira yang dipesannya.
Memang di meja makan, tidak ada pemecahan roti dan minum anggur, tetapi kehebatan perjamuan makan malam itu sungguh terasa karena semua makanan dilahap tuntas tak bersisa. Bahkan Romo Maryo tidak segan-segan menghabiskan ikan hingga tulang kepala terakhir.
Malam itu, Romo Maryo yang berkulit hitam mengulangi undangannya agar saya hadir dalam pesta 40 tahun imamatnya di Yogyakarta. Saya agak ragu, apakah pesta 40 tahun imamat atau 30 tahun, karena jika usianya 60 tahun dan dikurangi 40 tahun berarti Sumarya menjadi imam ketika baru berusia 20 tahun. Rasanya tidak mungkin. Yang paling tepat adalah ultah imamat ke-30 dan hidup membiara ke-40.
Namun dalam pesan lewat BB dan undangan di meja makan itu, Romo Maryo tetap menggunakan 40 tahun imamat, Kamis, 31 Oktober 2013. Tanpa perlu beradu argumentasi, pengulangan undangan itu merupakan perintah bagi saya untuk hadir. Pastor penyuka Gudang Garam Surya 16 itu menawarkan undangan resmi tapi saya menolak membawa undangan resmi. “Kalau tidak membawa undangan dan ditolak oleh panitia, nanti saya nunggu di luar aja, Mo,” jelas saya.
Janji untuk hadir dalam pesta syukur imamatnya, saya tegaskan kembali dengan mengatakan, “Sampai ketemu hari Kamis ya Mo!” sambil melambaikan tangan saat Romo Maryo meninggalkan saya di teras lobi Starbuck, Mall SMS, Gading Serpong, pukul 21.30.
Usia empatpuluh tahun dalam kehidupan imamat adalah luar biasa karena menghilangkan jati diri dan menukarnya dengan ketaatan mati kepada komunitas, kesetiaan kepada pimpinan serta menjaga kesucian seumur hidup.
Romo Maryo adalah “wong ndeso yang baik,” ujar Pastor Hariyanto SJ, rekan seangkatannya dalam Misa Requiem, 27 Oktober 2013, pukul 20.00 di Kapel Kanisius, Jakarta. Artinya, Romo Maryo tak pernah dapat dibelokkan ketika memegang prinsip dan menjalankan aturan. Mungkin itu terbentuk karena ia tidak memiliki latar belakang pengelolaan paroki. Yang dilakukannya adalah mengelola institusi Gereja dan cara pandangnya pun terhadap suatu masalah sangat sederhana, polos, tidak berbelit-belit.
Kesederhanaan itulah yang mungkin sangat tepat dilekatkan pada kepribadian Romo Maryo, termasuk dalam membina siswa-siswanya. Saat menikmati cappuccino di Coffee Bean setelah beranjak dari Salsa Foodcourt, Romo Maryo mengatakan kepada empat siswanya, “Nikmati surga dunia yang ada di mall ini dan bandingkan dengan kehidupan kemudian yang akan dihadapi.” SMS Gading Serpong yang disebut Romo Maryo sebagai surga dunia adalah mall keluarga karena begitu banyak pasangan muda dan anak-anak datang ke tempat itu.
Dengan polosnya, Romo Maryo melanjutkan pernyataannya, “Tapi yang jelas kalian berempat harus jadi pastor. Harus jadi pastor…” Menurut Romo Maryo, “Tidak ada cerita seorang romo atau pastor mati karena tidak mendapat makan.” Seorang imam tidak pernah akan mati kekurangan makan. Logika dan alasan yang sangat sederhana.
Saya masih ingat, ketika di Coffee Bean, Romo Maryo berulangkali melihat jam dan menyatakan ingin segera pulang karena Minggu pagi, mereka harus bangun pukul 04.00, kemudian melakukan pemanasan dan pukul 04.30 akan segera ke Monas mengikuti marathon.
Saya sarankan pulang pukul 21.00 dan membeli roti Breadtalk untuk sarapan pagi sebelum marathon. Kami pun beradu argumentasi mengapa harus mengisi perut sebelum lari dan makanan yang dimakan harus netral agar perut tidak berulah. Usulan saya diterima dan kami semua menuju outlet Breadtalk.
Pukul 21.30 setelah mendapatkan roti keinginan masing-masing Romo Maryo dan rombongan kembali ke Kanisius, Jakarta. Saya melepas para tamu dengan kebahagiaan tersendiri karena sudah memenuhi janji untuk makan bersama.
Namun, kebahagiaan yang saya alami hanya bertahan sembilan jam. Berita duka meninggalnya Romo Maryo saya terima Minggu pagi. Alasan kematian Romo Maryo itulah yang menjadi tanda tanya saya, karena rentang waktu antara pukul 04.00 dan 06.30, saat kematiannya, dia tidaklah lama.
Dikabarkan Romo Maryo terjatuh ketika berlari di depan Hotel Pullman Bundaran Hotel Indonesia. Itu artinya jarak tempuh belum separuh dari lima kilometer yang ditetapkan. Ia meninggal dalam ambulans yang membawanya ke rumah sakit.
Misteri kematian Romo Maryo menjadi jelas ketika Tri Novi Riastuti, seorang penerima renungan hariannya, mengatakan bahwa rektor Seminari Mertoyudan itu masih mengirim naskah renungannya pukul 02.15. Jika tidur pukul 02.30, berarti Romo Maryo hanya istirahat 1,5 jam. Artinya juga, secara fisik ia sangat lemah untuk mengikuti marathon.
Kenyataan, Romo Maryo masih melakukan pembicaraan dengan Pastor Ignatius Ismartono SJ pukul 03.00. Romo Maryo memang tidak istirahat sepanjang malam dan tidak sadar bahwa kondisi itu sangat berbahaya untuk mengikuti lari marathon bagi orang yang berusia di atas 60 tahun.
Romo Maryo sudah menyelesaikan hidupnya dalam kesederhanaan dan kepolosannya. Beliau menutup masanya dengan senyuman, gelak tawa dan juga “cerewet”. Empat puluh tahun, empat siswa seminari, jam empat adalah angka misteri yang tidak pernah terlupakan.
Namun keinginan Romo Maryo untuk mendapat liputan luas atas dirinya kesampaian juga. Sejak berpulangnya hingga pemakaman di Girisonta, 29 Oktober 2013, dihadiri banyak rekan wartawan dari berbagai media.
Tetapi yang mengejutkan, sepertinya Romo Maryo sudah membuat tanda-tanda atas kematian dirinya. Ia ternyata menulis artikel “KEMATIAN” yang dimintanya dimuat di Harian Kompas. Menurut seorang wakil pemimpin redaksi Tribun, artikel itu dititipkan kepada seseorang untuk diberikan kepada Redaksi Kompas.
Lalu? Selamat jalan romo, selamat berpesta imamat di surga. Terimakasih untuk The Last Suppernya!***
*AM Putut Prabantoro adalah moderator emiritus Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) dan Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) yang pernah belajar di Seminari Mertoyudan