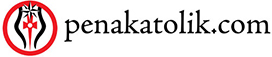Meski belum atau tidak digunakan di seluruh keuskupan di Indonesia, namun nama atau istilah “lingkungan” sebagai komunitas yang lebih kecil dari sebuah paroki sudah banyak digunakan oleh Gereja Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
Ada keuskupan yang menggunakan istilah lain seperti kring, wilayah, atau kelompok umat basis dan komunitas basis gereja, padahal, menurut Uskup Agung Jakarta yang juga Administrator Apostolik Bandung Mgr Ignatius Suharyo Pr, “kalau istilah ‘lingkungan’ dipahami maka menjadi sangat inspiratif.”
Mgr Suharyo berbicara di depan wakil-wakil semua paroki, komisi, sub-komisi, biro, kelompok kategorial, lembaga hidup bakti, dan yayasan di Keuskupan Bandung dalam Raker Tengah Tahun 2013 di Lembang, 21-22 Juni 2013.
Lingkungan atau kring (bahasa Belanda) yang sekarang dipakai di mana-mana, menurut Mgr Suharyo, diawali oleh Pastor Albertus Soegijapranata SJ waktu menjadi pastor kepala di Paroki Santo Yusuf Bintaran, Yogyakarta.
Menurut Ketua Presidium KWI itu, di tahun 1934 atau sebelum Indonesia merdeka, “sudah ada kring atau lingkungan” dan tempat munculnya ide, Gereja Santo Yusuf Bintaran, menjadi sangat penting.
“Kalau pergi ke Yogyakarta, di sana ada dua paroki yang saling berdekatan, mungkin hanya 400 meter, yang diantarai oleh Kali Code. Yang sebelah Barat namanya Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kidul Loji dan sebelah Timur namanya Paroki Santo Yusuf Bintaran. Sebelum Paroki Bintaran, sudah ada Paroki Kidul Loji,” Mgr Suharyo bercerita.
Saat itu, tahun 1934, lanjut cerita itu, “Paroki Kidul Loji adalah gereja untuk orang-orang Belanda yang kulitnya putih. Orang pribumi pun semakin banyak menjadi Katolik. Belum ada Indonesia waktu itu. Untuk yang pribumi dibuatkan gereja, Gereja Santo Yusuf Bintaran, karena mereka tidak boleh masuk ke Gereja Kidul Loji.”
Jadi, jelas uskup agung, gagasan lingkungan tidak lahir di Gereja Kidul Loji, tetapi di Gereja Bintaran. “Itu artinya ‘lingkungan’ menjadi salah satu ciri khas dari Gereja ‘Pribumi,’ ciri khas Gereja Indonesia.”
Ketika Pastor Soegijapranata memulai sistem lingkungan, yang dipikirkan hanyalah “supaya orang Katolik tidak saja berkumpul di gereja pusat, tetapi juga berkumpul di tengah-tengah masyarakat.”
Diakui, sumber ide tahun 1934 itu sangat jauh ke depan, yang kemudian dirumuskan 30 tahun kemudian dalam Konsili Vatikan II, “Romo Soegijapranata melihat begitu jauh ke depan bahwa Gereja Indonesia tidak mungkin hidup, tidak mungkin dapat berkembang, kalau tidak hadir di tengah-tengah masyarakat.”
Maka, kata Mgr Suharyo, dianjurkan supaya orang-orang Katolik berkumpul juga di lingkungan-lingkungan kecil, bukan hanya sekedar berkumpul tetapi berdoa dan berbicara bersama-sama mengenai keadaan masyarakat lingkungan, “yang sekarang dikembangkan menjadi Aksi Puasa Pembangunan.”
Tahun 1974, seorang misionaris Belanda menulis satu artikel dalam sebuah majalah Belanda dengan judul yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan “Lingkungan: Menuju Gereja yang Lain.”
Itu berarti, lanjut uskup agung, misionaris itu mengamati bahwa dengan sistem lingkungan selama 40 tahun Gereja Indonesia menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan Gereja Eropa yang di tahun 1070-an sudah mulai merosot sesudah Konsili Vatikan II.
Gereja di Indonesia kini menjadi sangat berbeda, semakin hidup, semakin manusiawi, dan salah satu kuncinya adalah lingkungan, “yang bagi saya adalah trade mark Gereja Indonesia, sekurang-kurangnya yang saya tahu di Pulau Jawa, karena mungkin agak sulit di tempat lain yang umatnya tinggal berjauhan sampai 10-15 kilometer,” kata Mgr Suharyo.***