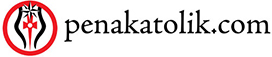Para misionaris pertama yang datang dari tahun 1808 sampai 1859 ke Batavia adalah para pastor praja atau diosesan dari Belanda dengan pikiran untuk melayani kebutuhan rohani orang Katolik Belanda dan Eropa. Mereka tidak berfikir untuk mewartakan iman di kalangan pribumi atau inlander karena bahasanya sulit bagi mereka dan sebagai misionaris yang digaji pemerintah Belanda mereka hanya bekerja untuk kalangan orang Belanda. Mgr Vrancken sendiri mengakui kesulitan mewartakan iman Katolik di kalangan suku Jawa.
Vikaris Apostolik itu mengatakan, “Di pulau Jawa, kita mempunyai lima pusat misi. Pekerjaan misionaris di pulau ini dikhususkan untuk orang-orang Eropa dan keturunannya. Orang-orang pribumi di Jawa seluruhnya Muslim dan mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa tertarik dengan agama Katolik. Pulau Jawa sendiri mempunyai penduduk 5 juta yang semuanya Muslim dan sampai sekarang belum ada yang mau masuk agama Katolik. Tidak ada banyak harapan bahwa dalam waktu dekat, mereka akan mau menjadi katolik.”[1]
Sejak tahun 1859 misionaris praja digantikan oleh Ordo Yesuit. Dua Yesuit pertama yang datang, Pastor van den Elzen dan Pastor Palinckx, juga melihat bahwa tidak ada tanda-tanda orang Jawa berminat belajar agama kristiani. Menurut mereka ada dua alasan. Pertama, karena kehidupan sosial dan kultural orang Jawa ditentukan oleh adat dan kokohnya persaudaraan antarkampung, dan karena semua orang beragama Islam, maka tidak ada satu pun orang Jawa yang berani untuk berbeda. Kedua, karena perilaku orang Eropa sendiri yang buruk menurut pandangan orang Jawa, seperti minum minuman keras dan juga mereka bangsa penjajah. Agama Katolik dianggap sama dengan agama penjajah. Kalau ada orang mau jadi Katolik berarti ia mau jadi orang Belanda. Jadi beban historis dan psikologis pewartaan iman Katolik di antara orang Jawa adalah sangat berat.
Para Yesuit terkenal dengan karya-karya misi di seluruh dunia. Mereka berkeliling dunia sampai ke lembah Amazon di Amerika Latin, pergi ke pulau-pulau di Maluku dan juga berhasil di Jepang. Maka diutuslah dua orang untuk mewartakan iman Katolik di Jawa Tengah yaitu Pastor Franciscus Gregorius Josephus van Lith dan Pastor Petrus Hoevenaars. Keduanya kemudian dikenal sebagai dua misionaris hebat di Jawa. Namun, mereka terkenal juga karena pertentangan tajam di antara keduanya. Metode bermisi mereka berbeda akibat perbedaan visi mereka. Pastor van Lith ingin mengenal budaya Jawa dan Orang Jawa terlebih dahulu baru kemudian mengajari agama dan membaptis. Pastor van Lith tidak mau tergesa-gesa membaptis. Sebaliknya, Pastor Hoevenaars memakai metode membaptis sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat supaya umat Katolik bertambah dengan cepat. Akibatnya, pimpinan Yesuit di Belanda mendapat kesan bahwa Pastor Hoevenaar berhasil dan Pastor van Lith gagal. Ketika Mgr Staal SJ berkunjung ke pusat misi Pastor van Lith di Muntilan, memang nampak bahwa misi itu seperti tidak menghasilkan buah.
Pastor van Lith sendiri mengeluh atas banyaknya kesulitan dalam mewartakan iman Katolik di antara orang Jawa Tengah: “Pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa ini adalah salib yang berat untuk saya. Sedikit kesuksesan yang dibarengi dengan tuduhan adalah surga di dunia ini. Semua tindakan baik dihargai dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku harus menenangkan pikiranku saat ini: nafsu makan dan kegembiraan lenyap. Saya tidak mempunyai antusiasme dalam pekerjaan saya maupun seluruh karya di tempat ini…”[2]
Tuhan menolong Pastor van Lith yang putus harapan dengan suatu mujizat. Ada empat orang datang dari Kalibawang ke Muntilan untuk memohon pengajaran agama Katolik untuk mereka dan untuk orang sekampungnya. Empat orang itu kemudian dibaptis di Muntilan tanggal 20 Mei 1904. Tujuh bulan kemudian Pastor van Lith membaptis 171 orang di Sendangsono tanggal 14 Desember 1904. Salah satu dari empat orang yang dibaptis di Muntilan itu adalah Sariman yang kemudian diberi nama Barnabas Sariman Sarikrama.
Sariman adalah pemuda dari desa Jamblangan, di pegunungan Menoreh yang lahir tahun 1874. Setelah menikah ia memakai nama tua (jeneng tuwa) Soerawirja (dibaca: Surawiryo) sesuai adat kebiasaan Jawa. Hidupnya penuh dengan kemiskinan dan penderitaan sejak kecil, maka ia terbiasa matiraga dan bersemèdi. Bahkan setelah beberapa lama menikah ia menderita sakit kaki sehingga tidak bisa berjalan. Ia harus bergerak dengan ngesot, yaitu berjalan dengan pantat dan ditopang oleh kedua tangannya, karena kakinya lumpuh. Untuk mencari kesembuhan, ia sudah melakukan laku tapa di Sendang Semagung di dekat desanya. Namun ia tidak sembuh. Kemudian secara aneh ia seperti mendapatkan wangsit, atau ilham atau bisikan dalam hati untuk berjalan ke arah timur laut. Dengan keyakinan teguh atas dorongan kuat yang misterius itu akhirnya ia sampai di Muntilan, yang berjarak sekitar 20 km dari desanya. Sesampai di pinggir jalan sebelah Gereja Katolik, kebetulan saat itu Pastor van Lith SJ sedang menyeberang jalan untuk sekedar berjalan-jalan mencari angin. Melihat Sariman yang berjalan ngesot itu, spontan Pastor van Lith membopongnya ke pastoran dan minta kepada Bruder Th Kersten SJ untuk merawatnya.[3]
Siapa menyangka bahwa ternyata Sariman itu, yang kemudian dibaptis Katolik dengan nama Barnabas dan namanya diubah oleh Pastor van Lith dari Soerawirja menjadi Sarikrama, adalah tokoh atau katekis yang ada di belakang layar sampai terjadi pembaptisan 171 orang di Sendang Sono tanggal 14 Desember 1904. Sendang Sono itu tidak lain adalah Sendang Semagung yang sudah lama dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat keramat di mana tinggal Dewi Lantamsari dan anaknya Den Baguse Samijo. “Barnabas Sarikrama, tatkala belum dibaptis, pernah juga bertapa di situ. Niatnya waktu itu ialah mencari kesembuhan bagi sakit kakinya. Beruntunglah sakit kakinya tidak sembuh, permohonannya tidak terkabulkan. Dan justru karena itu ia bertemu Pastor van Lith dan Bruder Kersten, dan disembuhkan.”
Cerita yang dituturkan Sarikrama (tentang kesembuhannya dan tentang perkenalannya dengan agama Katolik) menimbulkan decak kagum di hati penduduk desa Kajoran dan sekitarnya dan menimbulkan pertanyaan: Seperti apa wajah dan tampilan Kyai Londo itu? (Mereka belum pernah mendengar kata Pastor atau Romo), maka mereka hanya menyebut “Romo van Lith Kyai Londo”. Kyai adalah sebutan untuk tokoh agama Islam di kampung-kampung (isterinya disebut Nyai). Diam-diam pertanyaan itu muncul di benak orang-orang desa itu untuk kemudian menimbulkan hasrat kuat untuk mengikuti jejak Sarikrama untuk menjadi Katolik.[4]
Muntilan kemudian berkembang menjadi pusat misi Katolik untuk orang-orang Jawa. Melalui sekolah di Muntilan itu lahirlah para tokoh Nasional seperti Mgr Soegijopranata, uskup pribumi pertama dan I J Kasimo yang sudah menjadi anggota dewan sejak zaman Belanda (Volksraad) dan menjadi menteri pada zaman Presiden Soekarno. Melalui para lulusan sekolah guru, Muntilan mengirimkan mereka ke seluruh pelosok Jawa untuk menyebarkan iman Katolik. Perkembangan iman Katolik di Jawa Tengah itu kemudian menghasilkan umat Katolik yang baik dan tangguh di Keuskupan Agung Semarang, yang meliputi juga wilayah Yogyakarta dan Surakarta.
Pada zaman Pastor van Lith, ada seorang keturunan raja Jogya yang menjadi Katolik yaitu Maria Soelastri. Beliau ini juga adalah pendiri Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI). R Ay Maria Soelastri, lahir tanggal 22 April 1898, adalah putra kelima (puteri ketiga) dari Pangeran Sasraningrat, Putera Mahkota Sri Paku Alam III dan adik kandung R A J Sutartinah (isteri Ki Hadjar Dewantara).
Cerita di bawah ini saya ambil dari Sejarah Berdirinya WKRI yang ditulis oleh anggota Dewan Pengurus WKRI Ranting Ungaran Jawa Tengah: Sejak kanak-kanak sampai remaja, Soelastri Soejadi (baca: Suyadi) selalu ingin tahu mengenai kebudayaan bangsa lain, kebudayaan Barat dan aktivitasnya, budi pekerti dan kecerdasannya, untuk menjawab pertanyaan yang selalu ada dalam hati dan pikiran beliau mengapa tanah air kita dikuasai bangsa Barat dan terdesak hingga tinggal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Surakarta. DIY ini ada atas dasar persetujuan “Bedah Mataram” di desa Giyanti dekat Salatiga. Dalam perjanjian ini dicantumkan bahwa penjajah tidak dapat mencampuri pemerintah DIY. Itulah sebabnya rakyat Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang raja (Hamengku Buwono I) dan pengganti-penggantinya selalu waspada terhadap infiltrasi politik dari luar.
Ayahanda Soelastri Soejadi, Pangeran Sasraningrat, sangat menaruh minat pada Kesusasteraan Jawa Kuno dengan pergolakan-pergolakan dan perubahan jamannya. Kegiatan beliau dalam bidang jurnalistik membawa beliau berkenalan dengan tamu-tamu dari luar daerah, juga dari Batavia. Salah satunya adalah Dr Hazeu (adviseur voor inlandse zaken/penasehat urusan pemerintahan jajahan), yang membawa serta seorang anggota Misi Gereja Katolik untuk Jawa Tengah yaitu Pastor van Lith, yang kemudian sering berkunjung ke rumah bermaksud mempelajari Sastra Jawa, adat istiadat dan kebudayaan Jawa, agar beliau tidak membuat kesalahan dalam tugasnya mendekati bangsa Jawa untuk tujuan pembinaan lahir batin (pembinaan spiritual).
Kegiatan rumah tangga dengan banyak tamu ini menyebabkan suasana rumah penuh dengan diskusi. Pengetahuan mengenai sejarah bangsa Jawa, sejarah Majapahit, Demak, Mataram, Diponegoro dan Kesusasteraan Jawa diberikan oleh B R A (Bendara Raden Ayu) Sastraningrat, ibunda Maria Soelastri Soejadi, kepada seluruh putera puteri nya. Bekal dasar warna rumah tangga seperti inilah yang membawa Soelastri Soejadi menjadi cepat matang, memacu kedewasaan berpikir, membawa kematangan jiwa dan tumbuhnya iman Katolik “Mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan mencintai sesama manusia seperti pada dirinya sendiri”. Inilah penyempurnaan tingkah laku hidup bermasyarakat.
Tahun 1906, dengan rekomendasi Pastor van Lith dan disetujui ibunda B R A Sasraningrat masuklah Maria Soelastri ke Europeese Meisjesschool dari Ordo Suster Fransiskanes Kidul Loji Mataram, Yogyakarta. Tahun 1914, R Ay (Raden Ayu) Maria Soelastri Sasraningrat dipersunting oleh Dokter Hewan R M (Raden Mas) Jacobus Soejadi Darmosapoetro, yang meskipun pegawai negeri dalam pemerintahan tetapi berideologi politik melawan Politik Kapitalis Kolonial. Sebagai pendamping suami, Ibu Soelastri Soejadi ber-Tut Wuri Handayani dalam berpolitik. Setelah bekerja di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lombok, tahun 1923 Jacobus Soejadi sebagai single-fighter menjadi anggota Volksraad (DPR Belanda) dengan tugas mewakili seluruh umat Katolik pribumi di seluruh kepulauan Hindia Belanda. Soejadi menjadi pendamping dan pendorong suami yang setia.
Panggilan Tuhan untuk memikirkan nasib kaum wanita membuat Soelastri Soejadi mencari jalan keluar guna meningkatkan martabat dan mempersatukan wanita yang beragama Katolik. Pada masa pendudukan Belanda, kedudukan para buruh di Indonesia sangat buruk. Keadaan semacam ini juga terdapat di daerah Yogyakarta, tepatnya di Pabrik Cerutu dan Pabrik Gula yang mempunyai banyak buruh wanita Katolik atau calon Katolik. Dari buruh-buruh wanita inilah usaha peningkatan derajat dan martabat wanita pada umumnya dan wanita Katolik pada khususnya dimulai.
Soelastri Soejadi menghubungi kedua pemilik pabrik yang kebetulan beragama Katolik. Beliau mengadakan pendekatan dan berusaha mencari jalan untuk meningkatkan taraf hidup buruh-buruh ini dengan meningkatkan penghasilan mereka tanpa mengadakan pemogokan, karena pada waktu itu banyak terjadi pemogokan untuk menuntut kenaikan upah. Kepada kedua pemilik pabrik diterangkan bahwa sebagai seorang Katolik mereka harus menaati ajaran Gereja dalam hal ini Ensiklik Rerum Novarum, yang menurut Soelastri Soejadi belum diterapkan di kedua pabrik itu. Akhirnya kedua pemilik pabrik itu mengikuti petunjuk beliau. Usaha perbaikan nasib buruh dilaksanakan antara lain dengan membagikan tatiem (keuntungan) dari sebagian keuntungan perusahaan kepada para buruh. Pada masa itu pembagian keuntungan perusahaan kepada buruh tidak dapat disetujui perusahaan lain. Akibatnya pabrik gula tersebut dikeluarkan dari Ikatan Pengusaha Pabrik Gula.
Selain peningkatan ekonomi dan sosial para buruh ini, ada sebab lain yang mendorong didirikannya organisasi Wanita Katolik. Pada waktu itu telah berdiri Budi Utomo, Sarekat Islam. Tetapi ada anggapan umum yang mengatakan bahwa menjadi Kristen atau Katolik itu merupakan “balane Landa” (pengikut Belanda), anggapan yang tidak dapat diterima oleh para Katolik Pribumi (istilah pada waktu itu). Bagaimanapun juga umat Katolik harus menampilkan diri sebagai Katolik Pribumi (baca: Katolik Indonesia!). Khususnya untuk wanita Katolik dan demi kepentingan perbaikan nasib para buruh wanita, harus ada organisasi yang mengurusi wanita Katolik. Dengan mengumpulkan guru-guru lulusan Mendut dan dengan dukungan Pastor Henri van Driessche SJ, Soelastri Soejadi melemparkan gagasan untuk mendirikan Organisasi Wanita Katolik, organisasi dengan usaha ke arah pembentukan para wanita Katolik yang mengetahui dan menyadari kedudukannya di tengah kehidupan masyarakat : sebagai anggota masyarakat dan anggota Gereja. Gagasan disetujui, maka berdirilah Organisasi Wanita Katolik tanggal 26 Juni 1924.
Dalam perjalanan Organisasi Wanita Katolik ini, Soelastri Soejadi selalu menandaskan bahwa Organisasi Wanita Katolik ini bukanlah hasil impor dari negeri Belanda dan bukan usaha wanita Katolik negeri Belanda. Wanita Katolik Indonesia benar-benar lahir sebagai akibat desakan dan tuntutan masyarakat Indonesia sendiri. Adapun surat menyurat antara Soelastri Soejadi dengan wanita Katolik Belanda hanya bersifat personal atau pribadi dan bukan merupakan faktor penentu dalam lahirnya Wanita Katolik Indonesia. Tentang surat menyurat ini Soelastri Soejadi mengatakan pernah menerima surat tawaran bantuan wanita Katolik Belanda untuk wanita Katolik Pribumi (inlander). Jawaban Soelastri Soejadi benar-benar mengejutkan dan menggemparkan pihak wanita katolik Belanda. Surat jawaban itu diberi judul “Zonder tropen geen Nederland” (Tanpa daerah tropis, tidak ada Negeri Belanda), yang menguraikan dengan disertai angka-angka statistik hal-hal yang menyangkut kekayaan Indonesia yang telah diangkut ke negeri Belanda, dan sebagai akibatnya rakyat Indonesia menderita kemiskinan. Dalam surat jawaban itu juga ditandaskan bahwa sebenarnya rakyat Indonesialah yang telah memberi bantuan kepada rakyat Belanda. Jadi seharusnya wanita Katolik Belanda merasa malu karena terlambat menawarkan jasa”[5].
Kalau diperhatikan sampai hari ini, struktur umat Katolik di Jawa itu memang bermula dari keberhasilan Pastor van Lith dalam Misi Muntilan itu. Dari Muntilan tersebarlah iman Katolik melalui para lulusan sekolah guru Muntilan-Mendut ke pelbagai tempat mereka pergi. Penyebaran itu bukan hanya dalam arti geofrafis, melainkan juga strata sosial dan politis. Secara geografis, ke mana saja orang-orang Katolik suku Jawa itu pergi, mereka membawa iman Katolik. Secara sosial dan politis, tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan anggota umat Katolik suku Jawa masuk juga dalam bidang pemerintahan sudah sejak zaman Belanda (seperti dalam kasus di atas, Jacobus Soejadi) sampai zaman perjuangan kemerdekaan. Kita mengenal nama-nama Agustinus Adisoecipto, Ignatius Slamet Riyadi, Josaphat Soedarso dan Mgr Albertus Soegijopranata. Mereka adalah pahlawan nasional.
Kalau kita mengarahkan perhatian pada intern Gereja Katolik, maka kebanyakan uskup yang berasal dari suku Jawa, pasti berasal dari daerah Yogyakarta atau Keuskupan Agung Semarang yang adalah hasil misi dari Pastor van Lith. Semua Uskup Agung Jakarta berasal dari Jawa Tengah (Mgr Djajasepoetra SJ, Mgr Leo Soekoto SJ, Julius Kardinal Darmaatmaja SJ, dan Mgr Ignatius Soeharjo Pr). Belum ada putera daerah Jakarta atau Betawi yang menjadi uskup. Imam dari suku Betawi juga mungkin belum ada. Umat Katolik dari suku Betawi dan juga suku Sunda juga mungkin sangat sedikit. Uskup Bandung dan Bogor juga, setelah periode uskup Belanda selesai, digantikan oleh suka Jawa atau Flores, karena putera daerah Bandung dan Bogor juga sangat sedikit yang menjadi Katolik.Yang situasinya berbeda mungkin adalah daerah Keuskupan Malang yang sejak pemekaran prefekturat tahun 1927 diserahkan kepada Ordo Carmel dan Keuskupan Surabaya yang sejak tahun 1928 diserahkan kepada Imam Lazaris (CM).
Dengan mencermati “struktur umat Katolik suku Jawa” di Pulau Jawa itu, maka nampaklah benang merah dari sejarah bahwa keberhasilan misi Pastor van Lith dalam budaya Jawa itulah yang menjadi dasar dan motor penggerak Gereja Katolik di Pulau Jawa untuk seterusnya. Iman Katolik yang telah ditaburkan di daerah Muntilan-Mendut dan berkembang dalam Keuskupan Agung Semarang itu telah menghasilkan panggilan untuk menjadi imam, bruder, suster, uskup, dan kardinal, yang kemudian menjadi pimpinan Gereja Katolik di seluruh Indonesia. Beberapa uskup suku Jawa juga menjadi uskup di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Rupanya metode pewartaan iman Pastor van Lith yang mulai dengan mengenal budaya dan orang-orang Jawa terlebih dahulu, sebelum membaptisnya telah memberikan keberhasilan lebih besar daripada rekannya Pastor Hoevenaars yang memakai metode membaptis sebanyak mungkin tanpa pengenalan budaya dan pengajaran iman yang mendalam. Tahun 1904 Pastor Engbers (pimpinan Yesuit) memindahkan Pastor Hoevenaars dari Mendut ke Bandung. Karya Mendut dan Muntilah diserahkan kepada Pastor van Lith.(Sujoko)
- Tulisan ini merupakan tulisan ke-17 dari rangkaian tulisan Pastor Albertus Sujoko MSC berjudul “Jejak Allah dalam Sejarah”
[1] Mgr. Vrancken, “Rapport sur la Mission de Batavia” , Haarlemsche Bijdragen, 53/I. 1935.
[2] Hasto Rosariyanto, Father Franciscus van Lith SJ, hlm 216 – 217.
[3] St. S. Tartono, Barnabas Sarikrama, Orang Pertama Indonesia Penerima Bitang Kepausan, Musium Misi Muntilan, 2005, hlm. 21.
[4] Op.cit hlm 26.
[5] Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Ranting Ungaran, Jawa Tengahhttps://wkriungaran.wordpress.com/2008/12/15/wanita-katolik-republik-indonesia-sekilas-sejarah/ diunduh tgl. 1 Maret 2018 oleh Sujoko msc