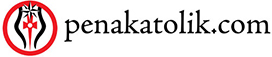LONDON, Pena Katolik – Konflik antara Mahkota Inggris dan Takhta Suci bermula pada masa yang dikenal sebagai Reformasi Inggris. Periode ini ditandai dengan penolakan terhadap yurisdiksi Paus di Inggris melalui “Deklarasi Supremasi Kerajaan” yang dikeluarkan oleh Raja Henry VIII. Langkah ini menegaskan bahwa raja adalah pemimpin tertinggi Gereja di Inggris, bukan Paus di Roma.
Keputusan tersebut segera diikuti dengan penyitaan harta benda Gereja, pembubaran biara-biara, eksekusi terhadap para imam yang setia kepada Roma, serta penerapan kebijakan wajib menghadiri ibadat Anglikan dan membayar persepuluhan kepada Gereja negara. Dalam waktu singkat, agama Katolik dinyatakan ilegal di seluruh Inggris.
Upaya untuk memulihkan hubungan dengan Roma sempat terjadi secara singkat pada masa pemerintahan Ratu Mary I, yang dikenal karena kesetiaannya kepada Gereja Katolik. Namun, kematiannya menandai berakhirnya usaha rekonsiliasi Gereja Inggris dengan Takhta Suci.
Ketegangan kembali memuncak pada tahun 1570 ketika Paus Pius V mengeluarkan ekskomunikasi terhadap Ratu Elizabeth I. Ia juga memberikan legitimasi bagi pemberontakan terhadap pemerintahannya. Tindakan tersebut memperkuat kecurigaan pihak kerajaan terhadap kesetiaan umat Katolik di Inggris.
Sebagai akibatnya, negara memperketat pengawasan dan menerapkan kembali berbagai bentuk penganiayaan. Umat Katolik hidup di bawah tekanan hukum yang keras selama berabad-abad, termasuk larangan untuk menjalankan ibadat secara terbuka, memiliki hak politik, atau menduduki jabatan publik. Baru tiga abad kemudian, serangkaian reformasi legislatif pada abad ke-19—yang dikenal sebagai Catholic Emancipation—perlahan-lahan menghapus sebagian besar pembatasan tersebut.
Meskipun demikian, satu larangan tetap bertahan hingga kini: seorang penganut Katolik Roma tidak dapat naik takhta Kerajaan Inggris. Namun sejak diberlakukannya Succession to the Crown Act pada tahun 2013, pernikahan dengan seorang Katolik tidak lagi menjadi penghalang bagi garis suksesi kerajaan. Perubahan ini menjadi simbol rekonsiliasi panjang antara dua tradisi iman yang dahulu terbelah oleh sejarah dan kekuasaan.

Gerakan Oxford hingga Konsili Vatikan II
Memasuki abad ke-19, sebuah arus pembaruan muncul di tubuh Gereja Inggris melalui Gerakan Oxford (Oxford Movement). Tokoh utama gerakan ini adalah St. Yohanes Henry Newman, yang dianugerahi gelar Pujangga Gereja oleh Leo XIV.
Saat itu, para teolog dan rohaniawan yang tergabung di dalamnya—kelak dikenal sebagai Anglo-Katolik—mendorong pemulihan unsur-unsur tradisional dalam liturgi dan spiritualitas yang telah lama dihilangkan sejak Reformasi. Mereka menilai bahwa praktik ibadat Anglikan telah menjadi terlalu sederhana dan kehilangan kekayaan rohani warisan Gereja.
Dalam tulisan ke-90 dari seri Tracts for the Times, St. Yohanes Henry Newman mengemukakan gagasan bahwa ajaran-ajaran Gereja Katolik Roma, sebagaimana didefinisikan dalam Konsili Trente, sejatinya tidak bertentangan dengan “Thirty-Nine Articles” Gereja Inggris abad ke-16. Pandangan ini menjadi jembatan awal menuju dialog yang lebih terbuka antara kedua tradisi.
Meski Catholic Emancipation di Inggris telah mengurangi ketegangan, persoalan teologis tetap membara. Pada tahun 1896, Paus Leo XIII menerbitkan bulla Apostolicae curae yang menyatakan bahwa tahbisan suci Anglikan “benar-benar batal dan sama sekali tidak sah.” Dokumen ini juga menolak teori “ranting-ranting Gereja” (branch theory) serta klaim suksesi apostolik dalam Gereja Anglikan. Sebagai tanggapan, dua Uskup Agung Gereja Inggris menerbitkan Saepius officio, yang mempertahankan keabsahan tradisi mereka. Hingga kini, keputusan Apostolicae curae tetap menjadi sikap resmi Takhta Suci.
Upaya rekonsiliasi tidak berhenti di situ. Pada awal abad ke-20, dibuka sebuah babak baru melalui “Malines Conversations”. Dialog ini dimulai tahun 1915 ketika Paus Benediktus XV menyetujui pembentukan Legasi Inggris untuk Vatikan. Pembicaraan antara perwakilan Anglikan dan Katolik ini sempat menumbuhkan harapan besar akan persatuan, namun akhirnya terhenti pada tahun 1925.
Meski demikian, benih dialog tetap tumbuh melalui gerakan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani, serta berbagai kunjungan persahabatan seperti pertemuan antara Uskup George Bell dari Chichester dan Kardinal Giovanni Battista Montini, yang kelak menjadi Paus Paulus VI.
Terobosan sejati baru terjadi pada masa Paus Yohanes XXIII yang membuka jalan bagi semangat ekumenisme melalui pembentukan Sekretariat untuk Promosi Kesatuan Umat Kristiani. Inisiatif ini mendorong Uskup Agung Canterbury, Geoffrey Fisher, melakukan kunjungan bersejarah ke Vatikan pada tahun 1960—kunjungan pertama sejak Reformasi, meskipun belum bersifat resmi.
Langkah ini disusul dengan kehadiran delegasi pengamat Anglikan dalam Konsili Vatikan II, yang dipimpin oleh Uskup John Moorman dari Ripon. Momentum persaudaraan semakin nyata ketika pada tahun 1966, Uskup Agung Canterbury Michael Ramsey mengunjungi Paus Paulus VI secara resmi. Dari pertemuan itulah lahir Komisi Internasional Anglikan-Katolik Roma (ARCIC) pada tahun berikutnya, yang menjadi wadah dialog teologis mendalam antara kedua Gereja.
Paus Paulus VI bahkan menyebut Gereja Anglikan sebagai “Gereja Saudari yang Terkasih,” sebuah ungkapan yang menandai perubahan besar dalam hubungan kedua pihak. Meskipun jalan menuju kesatuan penuh masih panjang dan penuh tantangan, semangat persaudaraan yang lahir dari abad ke-19 hingga era Konsili Vatikan II menjadi dasar kuat bagi dialog dan kerja sama ekumenis hingga hari ini.
Terus Menguat
Tonggak penting dalam hubungan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Anglikan terjadi pada tahun 1966, ketika Uskup Agung Canterbury, Michael Ramsey melakukan kunjungan resmi ke Paus Paulus VI di Vatikan. Pertemuan penuh persaudaraan ini menjadi simbol nyata dari keinginan kedua Gereja untuk memperbaiki hubungan setelah berabad-abad perpecahan. Dari kunjungan bersejarah tersebut lahirlah pada tahun berikutnya Komisi Internasional Anglikan-Katolik Roma atau Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC). Sebuah forum dialog teologis yang menjadi jembatan utama rekonsiliasi antara kedua Gereja.
Proyek pertama ARCIC berfokus pada otoritas Kitab Suci, dan sejak itu komisi ini telah menghasilkan sembilan pernyataan bersama (agreed statements) yang menjadi landasan pemahaman bersama mengenai berbagai ajaran iman. Tahap pertama ARCIC berakhir pada tahun 1981 dengan diterbitkannya laporan akhir berjudul Elucidations on Authority in the Church, yang membahas bagaimana wewenang dan otoritas rohani dijalankan dalam Gereja.
Tahap kedua berlangsung antara 1983 hingga 2004, dengan pembahasan yang semakin mendalam mengenai sakramen, keselamatan, dan peran Maria dalam sejarah keselamatan. Laporan terakhir tahap ini diterbitkan pada tahun 2004, menyoroti teologi Maria atau Mariologi, yang selama ini menjadi salah satu titik perbedaan utama antara kedua tradisi.
Untuk memperluas hasil dialog teologis menjadi kerja sama nyata di bidang pastoral dan sosial, pada tahun 2000—menyusul pertemuan para uskup Katolik dan Anglikan di Mississauga, Kanada—dibentuklah Komisi Internasional Anglikan-Katolik Roma untuk Kesatuan dan Misi (International Anglican-Roman Catholic Commission for Unity and Mission). Komisi ini bertugas mendorong kolaborasi praktis dan penerapan hasil-hasil dialog dalam kehidupan Gereja dan masyarakat.
Perbedaan dalam Mariologi, terutama terkait dogma Maria yang dikandung tanpa dosa dan Maria diangkat ke surga, sering menjadi bahan diskusi antara kedua Gereja. Namun, meskipun Gereja Anglikan tidak memiliki pandangan resmi mengenai dogma-dogma tersebut, kedua belah pihak telah berupaya membangun semangat kesatuan melalui dialog teologis yang saling menghormati.
Puncak dari upaya ini terwujud dalam dokumen bersama “Mary: Grace and Hope in Christ”, yang juga dikenal sebagai “Pernyataan Seattle”, diterbitkan pada tahun 2004. Dokumen ini menggarisbawahi peran Maria sebagai Bunda Yesus Kristus dan teladan iman bagi seluruh umat beriman, serta menegaskan bahwa refleksi teologis mengenai Maria seharusnya menjadi sarana untuk memperdalam kesatuan, bukan sumber perpecahan.
Melalui berbagai tahap dialog dan kerja sama ini, Gereja Katolik Roma dan Gereja Anglikan menapaki jalan panjang menuju kesatuan yang lebih dalam—sebuah perjalanan iman yang menandai bahwa rekonsiliasi sejati tumbuh dari kerendahan hati, saling pengertian, dan harapan akan kesatuan dalam Kristus.