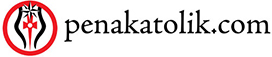JAKARTA, Pena Katolik – Mgr. Bernardus Bofitwos Baru OSA ditahbiskan sebagai Uskup Timika pada 15 Mei 2025. Sebelum memiliki uskup baru, Keuskupan Timika lama lowong, tepatnya sejak kepergian Mgr. John Philips Saklil pada Agustus 2019.
Ada harapan besar dengan kepemimpinan Mgr. Bernardus. Selama menjadi imam, ia aktif mengadvokasi situasi konflik di daerahnya. Ia berpendapat, negara belum benar-benar serius untuk menyelesaikan konflik di Papua.
“Konflik di Papua sifatnya konflik politik yang sudah lama. Ada juga persoalan investasi sumber daya alam. Tapi kan itu satu kesatuan soal politik,” ujarnya dalam sebuah wawancara yang dilakukan Tempo, 15 Maret 2025.
Dalam kacamata Mgr. Bernardus, tantangan yang dihadapi Keuskupan Timika tidaklah mudah. Ia menunjukkan bahwa selama ini Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Timika selama ini sudah bekerja untuk mengadvokasi pelbagai konflik di Papua. Usaha yang dilakukan termasuk berdialog dengan pihak-pihak terkait. Dari proses ini, ada data konflik yang juga terangkum.
“Jadi perlu ada pendekatan, dialog, komunikasi dengan pihak pemerintah, aparat, dan TNI,” ujarnya.
Tantangan lain yang dilihat Mgr. Bernardus adalah umat yang heterogen di mana umat terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Ia melihat, ketika konflik terjadi, umat dari luar Papua, tidak begitu aktif untuk merespons atau peduli, mereka skeptis dan menganggap itu bukan urusannya.
Mgr. Bernardus kemudian mengingatkan, sebagai umat Katolik, siapapun itu harus hidup bersama-sama, solider satu dengan yang lain.
“Kami ini kolegalitas, satu hati, satu jiwa, satu tubuh. Jadi mestinya anggota tubuh yang di kaki sakit, maka yang di kepala juga ikut terasa sakit,” ujar imam dari Ordo St. Agustinus ini.
Negara memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan konflik di Papua. Negara seharusnya memiliki peta untuk menyelesaikan masalah.
Dari sisi Gereja, Mgr. Bernardus melihat bahwa Gereja adalah mitra dari negara. Meski begitu, ia melihat Gereja memiliki ladang kerja lebih luas. Gereja tidak saja membangun umatnya, namun juga kesejahteraan materil, spiritual, moral, adat, dan budaya. Dengan demikian, negara perlu sekali berjalan bersama Gereja dalam penyelesaian konflik di Papua.
“Negara perlu menjadikan gereja sebagai mitra untuk menyelesaikan konflik itu. Saya kira itu penting. Negara tidak boleh menganggap gereja sebagai yang tidak perlu, atau sebagai musuh,” ujarnya.
Mgr. Bernardus menceritakan pengalamannya di Maybrat. Ia membangun dialog dengan pemerintah. Ia selalu mengingatkan jangan bermain konflik itu untuk kepentingan.
“Sudah menjadi tugas Gereja untuk menyampaikan itu,” ujarnya.
Mgr. Bernardus melanjutkan, Gereja adalah mitra negara. Ia menilai, konflik perlu diselesaikan secara kemanusiaan, lewat dialog, lewat medium untuk menyelesaikannya. Ia juga menyoroti situasi di Papua yang banyak terjadi extra judicial killing, pembunuhan di luar prosedur hukum tanpa melalui mekanisme.
Untuk itu, Mgr. Bernardus mendorong pemerintah untuk melihat Gereja sebagai mitra dan lebih banyak mendengarkannya, khususnya di Papua. Hal ini karena Gereja memiliki visi dialog, visi damai.
“Pemerintah belum cukup berdialog dengan gereja,” tegasnya.
Mgr. Bernardus berpendapat, negara justru menyelesaikan konflik ini dengan jalur-jalur yang bertolak belakang dengan sikap Gereja.
Seharusnya duduk berbicara, baru menyelesaikan konflik. Makanya Gereja selama ini berseru supaya menciptakan damai dengan cara dialog. Gereja sudah melakukan upaya dialog itu sejak lama.”
Perlu ada political will dari pemerintah untuk memediasi, berdialog dengan Gereja agar menyumbang pikiran, potensi yang ada untuk sama-sama menyelesaikan konflik di Papua.
“Tujuannya agar Papua menjadi damai, manusianya damai. Siapa saja yang datang atau tinggal di Papua bisa damai. Kami sama-sama hidup dalam suka cita, tidak bermusuhan.”