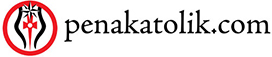PONTIANAK, Pena Katolik | Senin, 05 Agustus 2024- Keterkaitan globalisasi kebudayaan makan(an) mi instan dengan kecenderungan untuk massalisasi rasa produk secara global dapat dicermati dari paling tidak tiga industri mi instan yang memperkenalkan beragam rasa baru. Jelas ini bukan sebuah kebetulan.
Belasan rasa baru: Spagheti Salsa, Pizza Plus, Chicken Viesta, BBQ Burger dan Sausage Grill, Chicken Lemon, Pizza Favourite, Spagheti Tomato & Cheese; Roasted Beef Burger; BBQ Sausage; Burger, Pizza dan Chicken Nugget ini sangat jelas meningkatkan konsumen pada selera rasa makanan Barat yang lain.
Pengenalan selera rasa untuk mi instan seperti itu mudah diduga adalah karena memudahkan dan mendekatkan imajinasi konsumen dengan popularitas berbagai makanan cepat saji yang diimpor dari dunia Barat seperti tersedia di restoran-restoran: McDonald, Wendy’s, Burger King, Pizza Hut, dll.
Dalam hal ini, ABG adalah golongan yang mempunyai selera dan gaya hidup (peka zaman) yang mudah berubah-ubah. Mi instan adalah jenis makanan peka zaman.
Kisah lain tentang popularitas bakmi di Yogya dapat memberi contoh bagaimana nasi yang semula menjadi satu-satunya makanan pokok, tergusur oleh makanan mi instan akibat modernisasi dan urbanisasi gaya hidup konsumen.
Bukan sekedar kebetulan atau bahkan kesengajaan demi kepentingan promosi bisnis belaka kalau membaca kisah sukses seorang pengusaha restoran bakmi berikut ini. Bagi konsumen di kota Yogya, bakmi ternyata telah menjadi pesaing atau alternatif yang cukup memasyarakat terhadap kebiasaan makan nasi.
Semula memang ada mitos (Barthes, 1972), yang menyatakan bahwa “orang mudah merasa belum makan kalau belum menyantap nasi.”
Sesudah beberapa lama menekuni bisnis makanan, Bambang Benny Si, pemilik restoran “Mie Nusantara” di Yogya (Malioboro Mall) bercerita tentang langgananya sebagai berikut: Katanya, “Alhasil mereka pun ketagihan dan merasakan bahwa mi ternyata bisa membuat perut kenyang, dan enak” (KR, 21 Februari 2000).
Restoran ini terletak di sebuah mal dengan keuntungan yaitu mampu mendekatkan dagangan dengan konsumen.
Sehabis belanja di mal atau super market, misalnya, konsumen langsung menyantap mi dan tak perlu lagi memasak ketika tiba di rumah.
Sebuah strategi yang jeli ketika menyadari bahwa nasi cenderung bukan lagi satu-satunya makanan pokok dan merupakan keharusan bagi pola makan masyarakat Indonesia.
Begitu juga mi instan telah menggeser Jajan Pasar yang merupakan kebiasaan makan orang kebanyakan dan berfungsi sebagai makanan di luar makan besar; dalam arti tertentu dapat diartikan sebagai makanan sela di antara waktu makan.
Kehadiran mi instan ini pada gilirannya secara perlahan menggeser beberapa jenis makanan yang semula biasa tersaji di meja makan.
Tatanan budaya (cultural order) diwujudnyatakan dalam tatanan benda-benda (order of goods).
Produksi adalah reproduksi kebudayaan dalam sistem benda-benda (system of objects). Dengan kata lain, barang-barang yang dikonsumsi sebenarnya merupakan penanda (signifiers) dalam sistem kultural dan sosial, dan sistem ekonomi kemudian merespons kode tersebut dengan memproduksi signifiers lain lagi (Sahlins, 1976).
Dengan menambahkan sayuran, daging maupun bumbu lain dalam menyajikan mi instan, maka mi instan dapat dimasukkan dalam kategori jenis makanan “berat”, Artinya, jenis makanan yang fungsinya dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok.
Meskipun selama ini memang muncul mitos bahwa “jika belum makan nasi, terasa belum makan”, mi instan telah menggeser nasi sebagai makanan pokok. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang membawa perubahan pada gaya hidup, tampaknya mitos tersebut mulai pudar.
Meningkatnya kemakmuran dan masuknya pengaruh gaya hidup barat melalui turisme dan bisnis telah mengubah selera dan perilaku konsumen (Nestor, 122, 2006).

Perilaku konsumen yang menganggap mi instan merupakan jenis makanan yang sifatnya mendadak tetapi “penambahan” gizi menjadi pertimbangan untuk menjadikan mi instan tidak lagi sekadar makanan biasa, tapi memiliki “citra” (Baudrillard) yang lebih baik sebagai makanan modern.
Dalam perbincangan tentang strategi lokalisasi produk global(isasi) seperti mi instan, sebuah politik ekonomi konsumsi global biasanya berstrategi memperhatikan kondisi tertentu dari kebudayaan lokal.
Misalnya, memproduksi mi instan dengan rasa yang sesuai dengan selera masyarakat setempat, dan dalam iklan-iklan promosi dagangnya memanfaatkan gambar, syair dan irama lagu dari seni budaya “nasional” yang sudah begitu akrab di mata dan telinga konsumen Indonesia.
Indomie beberapa kali mengeksploitasi beberapa bagian lagu nasional kebangsaan Indonesia lewat syair seperti “Dari Sabang sampai Merauke … dan seterusnya.” Yang dalam iklan televisi masih ditambahkan tayangan sebuah keluarga di mana si ayah adalah pilot pesawat terbang yang mempunyai pelanggan orang Arab dan orang asing lainnya.
Globalisasi sesungguhnya didukung dan dipacu oleh warisan pengetahuan dari zaman Pencerahan yang menggiatkan modernisasi dan industrilisasi dalam kehidupan di dunia ini.
Industrilisasi global makanan pop seperti mi instan itu menghasilkan beberapa kontradiksi, paradoks dan ironi dalam kehidupan. Batas-batas lokal (teritorial) dalam kehidupan ekonomi dan kebudayaan akhirnya menjadi semakin sulit untuk dipertahankan ketika harus berhadapan dengan suatu gaya hidup ekonomi dan kebudayaan global yang cenderung hanya menghargai segala sesuatu yang bersifat asal baru dan asal dapat terjangkau atau terbeli (Nestor, 122, 2006)
Kebutuhan akan suatu barang tidak lagi sederhana bahwa barang tersebut dipandang dari fungsi kegunaan semata, namun juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mampu mengikuti zamannya. Penampilan yang elegan dan mengikuti perkembangan zaman dapat menjadi kunci penerimaan makanan secara global.
Di dalam masyarakat kapitalisme global, sedikitnya terdapat tiga bentuk “kekuasaan” yang beroperasi di belakang produksi dan konsumsi sebuah produk, yaitu kekuasaan kapital, kekuasaan produsen, serta kekuasaan media.
Ketiga bentuk kekuasaan tersebut pada berbagai praktik sosial telah menentukan bentuk dan gaya, produksi dan konsumsinya. Dalam hal ini sebuah produk dapat menentukan status, prestise dan simbol-simbol sosial tertentu untuk para pemakainya (Bourdieu, 1979).
Bertitik tolak dari identitas dan kecenderungan gaya hidup tersebut—maka sikap atau perilaku dalam mengkonsumsi mi instan dapat dilihat melalui kemasan mi instan. Kemasan mi instan selalu berusaha membentuk citra dan mencobakan produknya bagi konsumen.
Iklan melalui media (massa) informasi merupakan alat yang paling efektif untuk membentuk kebutuhan terhadap produk melalui penyebaran informasi mengenai sebuah produk. Melalui iklan di media masssa orang didorong untuk mengkonsumsi produk yang diiklankan dan membentuk sebuah citra akan sebuah produk.
Dalam masyarakat yang dipengaruhi kapitalisme global, media (massa) informasi telah membentuk dan mencipta gaya hidup dengan memberi pendangan bahwa kepribadian, harga diri, dan kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui pembelian dan pemilikan sebuah barang komoditi. Makanan seperti mi instan sebenarnya adalah bagian dari strategi kerja normalisasi tubuh manusia.
Tubuh normal tak lain adalah sumber daya yang harus disiplin dan produktif menghasilkan sesuatu target tertentu bahkan dapat saja sampai membuat tubuh dan pikiran memang akan menerima kehidupan seperti tanpa mampu protes apapun.
Meskipun konsumen sadar akan apa yang menjadi keputusannya untuk mengkomsumsi mi instan meski mengandung bahan yang membahayakan tubuh tapi konsumen tidak mampu untuk berbuat lebih banyak.
Kenyataan ini membawa pemahaman lain, yaitu sesungguhnya menjadi begitu jelas sekali bahwa pola dan keinginan konsumsi bukan melulu di dasarkan pada nilai kegunaan semata. Berbagai nilai yang ada di luar nilai guna juga mempengaruhi keputusan mengkonsumsi (Nestor, 120, 2006). Dalam hal ini penggunan mi instan pun juga merujuk pada identitas dan status sosial tertentu yang di-imajinasi-kan konsumen.
Kelihatan modernitas telah menggeser pemaknaan orang akan makan dan makanan. Makanan ibarat bahan bakar untuk kendaraan karena memiliki nilai efisiensi (tidak memboroskan waktu). Yang terpenting bagi konsumen adalah makan sekedar mengisi perut supaya mereka tidak lapar dan dapat melanjutkan aktivitas berikutnya.
Didukung dengan daya magis iklan, mi instan tampaknya berhasil mengukuhkan diri sebagai makanan “peka zaman”.
Ingatan akan produk tersebut dibentuk melalui intensitas pesan mengenai siapa yang layak mengkonsumsi jenis makanan ini. Pemakaian sudut pandang atau bingkai keluarga sebagai latar iklan terhadap beragam merek mi instan di televisi, radio dan koran memelihara ingatan konsumen akan kebutuhan mi instan sebagai “bahan bakar” agar kendaraan dapat tetap berjalan.
Melalui mediasi iklan, ia bekerja dengan efektif untuk mendekatkan dan mengakrabkan makanan asing dan global ini dalam rumah tangga konsumen lokal, serta bagaimana “nilai lebih” makanan ini ditampilkan demi memenuhi “keamanan” pangan.
Konsumsi dalam masyarakat ekonomi global adalah imajinasi tentang pernyataan selera individual. Industri konsumen modern seolah hanya membaca apa yang secara alami dan permanen terkandung dalam selera dan citra rasa individual.
Perkembangan dalam pengolahan pangan modern membawa ide mengenai keunggulan pangan modern. Keunggulan ini memperoleh tempat dengan gagasan keunggulan kompetitif.
Dengan cara berpikir ini—atau lebih tepatnya cara ber-imajinasi –penemuan metode pengolahan modern makanan instan mendapat kekuatannya. Makanan yang diolah dengan teknologi yang lebih tinggi memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan makanan yang secara teknologi diolah dengan lebih sederhana.
Dalam hal ini, dikotomi biner antara makan tradisional dan makanan modern membuat makanan modern mampu diterima dengan lebih luas. Dikotomi biner ini membuka peluang masuknya nilai lebih dari makanan modern, misalnya seperti: kemasan yang bagus dan aman, kecukupan nilai-nilai gizi yang lebih terjamin, kebersihan, termasuk juga kemampuan untuk di simpan dan tahan lebih lama.
Hampir seluruh mi instan yang beredar di pasaran selalu bergambar suatu sajian atau semacam tata saji semangkuk mi.
Pengetahuan kemasan untuk produk makanan bisa jadi kurang begitu dipahami oleh konsumen. Mereka tidak terlalu memperhatikan informasi penting yang muncul dalam kemasan. Yang penting adalah mi tidak perlu bergizi baik karena bukan makanan pokok, tapi mampu membuat kenyang dan menghemat waktu: ready to eat, ready to cook, half cooked, dan ready to serve.
Hal ini menegaskan bahwa perilaku konsumen terutama tidak semata ditentukan oleh pikiran-pikiran (Ideal-isme) mengenai kebutuhan akan barang itu sendiri melainkan juga penetrasi iklan dan promosi visual yang begitu massif masuk dalam ingatan konsumen. Akibatnya, nasi atau bukan nasi tidak lagi terpikirkan. Kepentingan utama untuk mengkonsumsi makanan modern ini adalah sejauh praktis, efisien dan kenyang (Real-isme).
Menurut teori “tingkat kebutuhan”, perilaku konsumen bukan lagi semata-mata unsur rasionalitas ekonomi ataupun irasionaltas psikologis, tapi konsumsi telah menjadi rekayasa politik, ekonomi, dan budaya yang membuat orang-orang merasa “wajib ingin sesuatu”.
Meskipun konsumsi ada dalam setiap gerak kebudayaan manusia, namun baru beberapa dekade terakhir “konsumsi” dalam skala massa muncul sebagai dasar kehidupan daripada sebagai gejala kehidupan. Di mana terdapat proses produksi subsisten, di situ dipastikan konsumsi subsisten: “Semua yang diproduksi pasti dikonsumsi”.
Maka, tak heran kompetisi antar-status golongan yang beroperasi atas dasar pola-pola konsumsi, seperti yang kata Weber, menjadi kelihatan lebih penting daripada perjuangan antar kelas menurut Marx, yang beroperasi atas dasar pola-pola produksi.
Sebuah pola dasar yang ketika bergandengan dengan sistem industrilisasi global akan menghasilkan apa yang disebut kebudayaan massa (Smith, 2001) di mana masing-masing kelompok orang – siapapun dan di manapun – boleh dan dapat saling bertemu hanya di dalam pasar dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Di sini “konsumsi” semakin mendapat tempat sebagai sebuah “society drive.”
Dalam wajah kebudayaan semacam ini maka segera saja setiap wilayah, setiap orang, dan setiap celah kebutuhan adalah pasar. Bahkan untuk jenis-jenis kebutuhan yang dahulu hanya menjadi ruang “lokal” karena masih aktualnya konsep “otensitas” atau “privasi” atau bahkan “tabu”.
Semangat-semangat itu mengabur dalam suatu ruang besar yang disebut “pasar”, digantikan dengan citra dan makna baru (signification) yang sangat cerdik disampaikan oleh media komunikasi massa(l).
Dalam media komunikasi massa(l) modern selalu saja ada yang “lebih” baru, bukan saja makna-makna tapi juga konstruksi identitas (Nestor, 122, 2016). Setiap orang terhubung dengan televisi murni sebagai individu yang terjarak dari ikatan-ikatan sosial aslinya.
Di depan televisi setiap individu adalah anggota-anggota anonim dari kumpulan besar penonton yang abstrak sekaligus universal.
Kolektivitas yang lebih luas di mana seseorang sedang berada, atau nilai-nilai yang sedang dihidupinya, cenderung diabaikan, terkikis dan menjadi kepingan-kepingan.
Baik konsumerisme maupun televisi bukan sumber asli bagi identitas maupun nilai-nilai tapi karena tidak alternatif lain, maka budaya pop dan media massa tampil sebagai satu-satunya bingkai yang tersedia bagi konstruksi identitas kolektif maupun personal.
Orang perlu menyimak panduan gaya hidup yang lebih pop dan karenanya lebih “pas”. Begitulah media komunikasi massa(l) modern bukan saja mengutip moto sebuah produk “membuat jarak kian tak berarti” namun juga mampu membentuk identitas tertentu dan mengarahkan sikap manusia global.
Dan bagaimana ketika ternyata arahan-arahan itu adalah demi dominasi ‘kepentingan tertentu’ dalam proses globalisasi di segala bidang yang langsung maupun tidak langsung dapat bermuara pada suatu struktur ekonomi dan kebudayaan yang tidak adil?
Mi instan sebagai produk budaya pop; sebagai komoditi massa(l) berciri dominan dan peka terhadap kepentingan sepihak yang mengalir bersama cerdiknya peran media massa(l) modern dalam mengaburkan atau menyamarkan perbedaan antara imajinasi dan kenyataan menjadi penting.
Apalagi kemampuan media komunikasi massa(l) untuk menawarkan makna-makna dan citra yang “selalu saja ada yang lebih baru”. Sangat mungkin fantasi tentang “lebih baru” itu juga menentukan dan dengan begitu “mengarahkan dalam persoalan selera dan cita rasa, termasuk makanan.
Peradaban telah pula ikut merubah jejak langkah kebudayaan makan(an) manusia. Dan kini, dalam masyarakat di mana realitas adalah juga yang di-imajinasi-kan dan di-fantasi-kan (Nestor, 124-5, 2006), menyantap mi (secara) instan seolah sudah dapat merasai burger, pizza, sausage grill atau nasi uduk.
Sebuah fakta dan fiksi tentang kebudayaan. Fictio berarti juga sesuatu yang dikonstruksikan, ditemukan, dibuat, selain juga dibuat-buat. Fiksi adalah fiksi, tapi fakta juga fiksi.
Ditulis: H.Y. Suhendra. Dosen Filsafat dan Metodologi S2 & S3 SKSG Universitas Indonesia dan Unika Santo Agustinus Hippo, Kalbar.