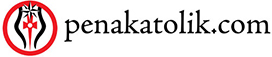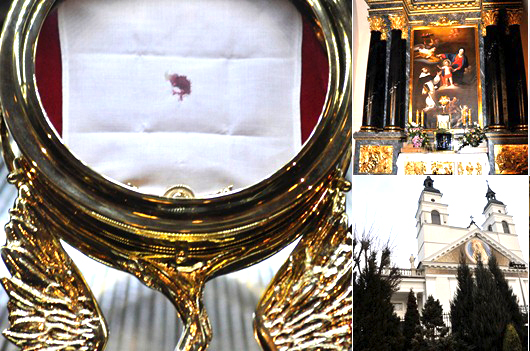Frater Rupinus Kehi*
Sebagai frater calon imam di Keuskupan Agung Pontianak, selama Pekan Suci 2019 hingga hari Selasa dalam Oktaf Paskah, saya mendapat tugas untuk mengunjungi delapan stasi dari 36 stasi dari Paroki Santa Maria Vianney Serimbu yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan Air Besar Serimbu. Kecamatan itu adalah salah satu kecamatan terluar di Kabupaten Landak, yang berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu Sanggau dan Bengkayang.
Paroki itu dilayani oleh dua imam yaitu Pastor Saut Maruli Tua Pr sebagai kepala paroki dan Pastor Marselus Andi Pr sebagai pastor rekan. Mereka dibantu oleh seorang frater yang sedang menjalani masa Tahun Orientasi Pastoral yaitu Frater Iko Logam. Saya sendiri sedang menjalani Orintasi Pastoral di STKIP Pamane Talino, Ngabang, yang merupakan sekolah tinggi milik Keuskupan Agung Pontianak yang baru dialihkelolakan Agustus 2018.
Dalam menjalani tugas perutusan ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Pertama, stasi-stasi yang saya kunjungi memiliki jarak yang cukup jauh, karena terletak di perbatasan atau daerah terluar dari kecamatan. Saya mencapai stasi-stasi itu dengan motor melalui jalanan panjang yang rusak, menanjak dan berlumpur, menyusuri hutan, perkebunan, tebing dan gunung.
Setiba di stasi-stasi itu saya juga mengalami dan belajar bahwa sangat rumit dan sulit bagi umat di pedalaman untuk belajar tata liturgi. Jangankan untuk menghayati, untuk mempersiapkan peralatan dan petugas saja umat sangat kesulitan. Jangankan untuk mendekorasi gereja, lilin saja mereka harus membagi sebatang lilin menjadi tiga. Jangankan sound system, listrik saja mereka tidak ada. Saya tidak dapat membayangkan betapa minimalisnya perayaan akan dilaksanakan jika beberapa tempat itu mendapat kunjungan imam, frater atau suster.
Saya yakin, keadaan itu bukan disebabkan karena ketidakmauan umat untuk belajar, tetapi media pembelajaran liturgi di sana sangat terbatas dan sangat mahal, apalagi menyadari bahwa kolekte mingguan mereka hanya berkisar 100 hingga 200 ribu rupiah.
Menyadari bahwa Gereja Katolik masuk ke wilayah itu baru sekitar tahun 1960-an, atau usianya masih terbilang muda, saya pun harus mengubah konsep renungan atau khotbah saya menjadi bahasa-bahasa yang sederhana agar biasa ditangkap umat.
Tetapi, dari keterbatasan-keterbatasan itu, saya menemukan satu kekaguman, yaitu semangat menggereja mereka. Meski gerejanya kecil dengan kursi dan hiasan seadanya, bahkan tidak memiliki listrik, mereka begitu bersemangat menyambut kedatangan para pelayan dari pusat paroki.
Seperti biasanya, setelah melaksanakan ibadah, mereka berkumpul bersama di salah satu rumah umat, dan biasanya di rumah pemimpin umat setempat, untuk makan bersama makanan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Di sana mereka bercerita bersama, tertawa bersama, bernyanyi bersama sampai larut malam. Bagi saya inilah Ekaristi sejati, tempat umat berkumpul di rumah dan makan bersama.
Dalam kesempatan itu, saya tidak lupa mengajak anak-anak muda untuk mengunjungi dan membawa komuni bagi orang tua serta orang sakit yang tidak bisa datang ke gereja.
Dalam perbincangan malam setelah ibadah, saya juga mengambil kesempatan untuk memberikan katekese sederhana, pembelajaran teologi dan pembelajaran kehidupan umat beriman sebagai komunitas Katolik. Saya merasa, katekese sederhana seperti ini sangat diperlukan bagi umat yang sangat jarang menerima kunjungan imam, frater atau suster karena banyaknya stasi di sebuah paroki dan karena sulitnya akses ke stasi-stasi itu.
Dengan motor sederhana, dengan jalan atau akses yang sama, saya pun berpindah ke stasi lain kemudian pulang ke Ngabang, bukan dengan stipendium uang yang sulit mereka berikan, namun aneka hasil pertanian, seperti beras, sayuran, makanan khas, dan lain-lain. Dan, meluncurlah motor saya dipenuhi aneka bahan makanan sebagai buah pelayanan dan ucapan terimakasih.***
*Calon imam diosesan Keuskupan Agung Pontianak