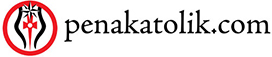Meskipun Yanghee Lee dari Korea yang bertugas sebagai pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar datang berkunjung sejak 9 hingga 20 Januari 2017, namun situasi kemanusiaan serius yang dialami kaum etnis minoritas Muslim Rohingya tidak berubah. Sekitar 1,2 juta orang itu tinggal di negara bagian Rahkine, di bagian barat Myanmar.
Ribuan warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena Pemerintah Burma tidak menganggap mereka sebagai warga negara, tetapi sebagai “imigran gelap.” Semua hak mereka dirampas. Status diskriminasi yang melembaga ini sudah berlangsung beberapa dekade, namun terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir ini.
Ketegangan-ketegangan sosial dan agama di negara bagian Rahkine sudah mulai di tahun 2012. Rohingya pun menjadi subjek kekerasan dan penganiayaan yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok nasionalis Buddha yang menghimbau negara mengusir mereka.
Menurut PBB, sedikitnya 100 ribu orang Rohingya telah lari mencari perlindungan di negara-negara tetangga, dan dalam minggu terakhir saja sekitar 22 ribu orang melakukan hal yang sama, setelah tentara Burma menyerang Rakhine, negara bagian utara, guna mencari “para pemberontak.” Menurut para LSM, kekerasan itu bisa mengkonfigurasi pelanggaran “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Sebanyak 150 ribu warga sipil Rohingya lain kini berada di kamp-kamp pengungsi dan membutuhkan bantuan kemanusiaan lengkap.
Pastor Stephen Chit Thein dari Keuskupan Pyay, yang mencakup Negara Bagian Rahkine, adalah penduduk asli daerah dekat Settwe, tempat populasi itu menetap. “Saya ingat kesulitan komunikasi dengan mereka, karena kami tidak tahu bahasa Burma,” kata imam itu kepada Fides. “Kami prihatin terhadap mereka, meskipun saat ini kami tidak punya perwakilan Katolik atau imam di sepanjang negeri itu. Hanya ada orang Buddha di sana. Kami tahu bahwa situasi kemanusiaan adalah hal serius, maka kami ungkapkan solidaritas kami, tapi bantuan masih sulit,” kata imam itu.
Gereja Katolik, dengan struktur dan organisasi amal kasihnya seperti Caritas, yang dikenal di Myanmar dengan nama “Karuna,” tidak dapat bertindak. “Pemerintah tak membolehkan kami memasuki wilayah atau kamp-kamp pengungsi. Tidak ada organisasi berbasis keagamaan bisa melakukannya dan hanya beberapa LSM internasional bisa membawa bantuan kemanusiaan,” lapor Pastor Nereus Tun Min, ketua “Karuna” di Keuskupan Pyay, seraya menegaskan bahwa “sekedar menjadi penonton krisis ini adalah melawan kehendak kami.”
Dijelaskan, mereka memahami bahwa orang Rohingya banyak menderita. “Kami tahu semua masalah mereka, mulai dari tidak adanya pengakuan negara, yang merupakan dasar semua ketidaknyamanan lain dan merupakan konsekuensi yang sangat membahayakan mereka.”
Ketua “Karuna” itu menyimpulkan: “Yang bisa kita minta, mengingat keberadaan Utusan PBB untuk Hak Asasi Manusia saat ini di Myanmar, adalah agar pemerintah yang baru bekerja sama menghentikan eskalasi ini dan membantu mengatur situasi yang sudah tidak dapat dipertahankan terus dari sudut pandang kemanusiaan itu dengan berupaya mencari solusi yang menghormati hak dan martabat setiap umat manusia.”
Sehubungan dengan cobaan yang dialami orang Rohingya, para uskup Burma pun sudah membicarakannya di masa lalu. Uskup Agung Yangon Kardinal Charles Maung Bo, ketika berbicara tentang fase baru demokrasi yang dimulai di bangsa itu, mencela “meluasnya kebencian dan penolakan hak,” yang mengacu pada kekerasan yang dilakukan oleh golongan pinggir Buddha terhadap umat Muslim Rohingya tetapi juga terhadap permusuhan yang diperlihatkan pemerintah Burma kepada mereka. Dalam situasi sulit ini dan lainnya serta dalam konflik sosial, orang Katolik Burma “bertugas membawa belas kasihan dan menyebarkan belas kasihan,” kata kardinal itu. (pcp berdasarkan tulisan PA dalam Agenzia Fides)