Oleh Pastor Johanes Robini Marianto OP
Peringatan 50 Tahun Konsili Vatikan (1962-1965) diperingati selama tiga tahun dan dibuka oleh Paus Benediktus XVI. Banyak pihak memuji hasil Konsili Vatikan II dan menyebutnya sebagai “gerakan Roh Kudus.” Pujian juga diberikan oleh Santo Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI. Memang di sana-sini terdapat banyak kritikkan bahwa Konsili Vatikan II (KV II) seolah-olah membuat Gereja terlalu adaptasi dengan dunia dan meremehkan tradisi lama Gereja Katolik. Namun, ekses bukan berarti KV II salah. Harus diakui, konsili merupakan ungkapan tertinggi tindakan (bukan hanya semangat) kolegialitas seluruh Gereja sehingga bersifat tidak dapat sesat (infalibilis). Maka menolak KV II dan hasilnya merupakan tindakan melawan karisma yang diberikan Roh Kudus yakni ketidakdapatsesatan dari Gereja Katolik.
Ekses negatif selalu ada karena banyak orang belum memahami semangat, isi dan keputusan KV II. Konsili Trente (1545-1563 M) begitu mengakar karena hasil-hasilnya lama dipraktekkan dalam Gereja. Trente boleh dikatakan menentukan hidup Gereja hampir 400 tahun! Maka tidak mengherankan kalau KV II belum sangat tersosialisasi karena baru 50 tahun. Penerimaan (reception) memerlukan proses. Belum tentu semua pihak mengerti ajaran dan semangat KV II.
Ketika Santo Yohanes XXIII membuka KV II, beliau menyampaikan pidato pembukaan berjudul “Gaudet Mater Ecclesia” (Bergembiralah Bunda Gereja). Isinya dapat diringkas demikian:
Pertama, dewasa ini banyak nabi palsu (prophet of doom) yang melihat dunia ini dalam status kejahatan, buruk dan serba hitam. Mereka lupa bahwa dunia itu juga diselamatkan oleh penebusan Kristus dan bahwa Allah dalam kasih-Nya selalu menemani manusia di dunia. Tuhan yang menciptakan dunia tentu akan menyelamatkannya. Maka mustahil bahwa dunia (modern, terutama) hanyalah berisi kejahatan dan kegelapan.
Kedua, Gereja akan lebih bersinar dan menginjili dengan baik dengan cara mewartakan “obat kemurahan hati” (medicine of mercy) daripada mengutuk. Iman Kristen harus diwartakan sedemikian rupa dari perbendaharaannya yang kadangkala terkurung oleh semangat kutuk-mengutuk. Orang lupa bahwa mewartakan keindahan dan kemuliaan iman Kristen lebih penting, sehingga orang yang mendengarnya menjadi tertarik dan masuk ke dalamnya. Belum tentu semua dunia itu gelap, karena Allah di dalamnya (the splendor of Christian Faith).
Ketiga, untuk tujuan di atas Santo Yohanes XXIII mengatakan bahwa Gereja perlu mengalami perubahan atau tepatnya pembaharuan. Banyak harta iman (depositum fidei) yang luar biasa perlu diwartakan secara baru dengan bentuk (form) boleh beda tetapi substansi (isi) tetap sama. Untuk pertama kalinya Gereja menerima pluralism (kebhinekaan) ungkapan iman tanpa mengkompromikan isi ajaran iman tersebut. Inilah keterbukaan KV II dan semangatnya yang disebut “aggiornamento.”
Keempat, dalam hubungan dengan dunia modern yang penting adalah semangat dialog bukan mengutuki. Dunia (modern) dan hasil karyanya juga ciptaan Tuhan. Akal budi yang penuh inovasi dan perkembangannya adalah karunia Tuhan. Maka mustahil Tuhan meninggalkannya pada si Jahat sehingga dunia gelap semua. Dunia adalah lahan penginjilan, tempat Tuhan berkarya menyelamatkan manusia. Ia juga berjanji selalu hadir menyertai umat-Nya di dunia (Mat 28:28). Maka, dunia tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan Tuhan ada di dalamnya. Mengatakan dunia jelek sama saja menolak keyakinan iman bahwa Tuhan ada untuk menyelamatkannya. Yang paling penting bagi Gereja adalah berdialog. Anggota Gereja hidup di dunia ini, bertatap muka dan berbicara dari hati ke hati (itulah arti dialog) untuk membawa manusia ke Tuhan dan Tuhan ke dunia (manusia). Oleh karena itu, dokumen Konstitusi Pastoral Untuk Dunia Dewasa Ini (Gaudium et Spes, GS) tegas mengatakan, “Duka dan kecemasan, harapan dan kesedihan, kegembiraan dan duka cita semua manusia di dunia adalah milik Gereja juga” (GS 1). Gereja mau menjalin temu wicara (GS 3) dengan sesama manusia juga yang bukan anggotanya. Inilah semangat baru yang harus dipahami untuk mengerti KV II.
Banyak pihak ekstrem membuat tafsirkan terlalu maju dan bebas dan menjadikan KV II seolah-olah mendukung mereka untuk bersikap bebas dalam pembaharuan. Akibatnya, bukanlah pembaharuan yang terjadi melainkan adaptasi total. Pihak yang menolak KV II juga melihat konsili itu penuh kontradiksi sehingga mereka mengambil sikap menolak atau tertutup. Kedua belah pihak lupa bahwa perkembangan dogma (ajaran iman) bersifat homogenus (tidak pernah menolak yang lama; tetapi mengintegrasikannya dalam tafsiran (hermeneutik) terang masalah baru yang dihadapi tanpa meninggalkan tradisi yang ada). Di zaman Tuhan Yesus, persoalan bayi tabung belum ada. Sekarang, persoalan bayi tabung harus ditafsirkan berdasarkan data wahyu sehinga didapatkan jawabannya untuk umat yang hidup di zaman ada bayi tabung. Maka, ini bukan proses buka Kitab Suci secara harafiah, melainkan proses tafsiran yang melibatkan tradisi iman dalam hubungannya dengan situasi sekarang. Kalau hanya melihat secara harafiah atau menutup diri bagi masalah baru, masalah tidak terselesaikan, karena dahulu belum ada.
Inti dari kedua sikap itu, menurut hemat penulis, adalah ketidakmampuan untuk menghadapi perkembangan dunia modern. Banyak orang tidak mau susah menfasirkan secara rumit dan dalam proses yang tidak gampang dan penuh tantangan. Mereka lebih enak potong kompas dengan cara “hitam-putih.” Awalnya, proses ini kelihatan penuh kepastian. Namun sebenarnya proses ini membuat Gereja menjadi museum kebenaran, bahkan fosil. Gereja adalah organisme yang hidup karena Roh menghidupkan. Menjadikan Gereja sebagai pengulangan masa lampau membuatnya menjadi fosil atau organisme masa lalu. Padahal Kristus kepala Gereja adalah “dahulu, kini dan selama-lamanya.” Maka, jangan hanya mengulangi masa lalu. Tetapi, memutuskan ikatan rantai dengan masa lalu sama saja menjadikan Gereja tidak punya arti lagi. Gereja itu bukan jatuh dari langit begitu saja. Gereja menjadi semakin matang melalui proses tradisi panjang. Ikatan dengan masa lalu adalah identitas dan bukan hanya masa lalu. Gereja juga adalah Umat Allah yang mempunyai sejarah.
Kedua sikap ekstrem itu sama-sama membuat Gereja menjadi fosil atau kehilangan identitas sejarahnya. Sebagai organisme yang hidup, manusia atau umat beriman harus selalu berusaha “mempelajari, merenungkan, mendoakan Sabda Ilahi sehingga pengertian semakin bekembang karena dorongan Roh Kudus (DV 12).” Ini merupakan tantangan karena banyak orang tidak mau terbuka, “malas” menjawab pertanyaan baru, dan lebih enak hidup dalam kepastian palsu dalam zona aman. Padahal, zona aman tidak ada dalam hidup iman, karena hidup bergerak terus menuju kepenuhan akhir jaman. Tidak ada yang abadi di dunia ini selama masih di dunia ini.
Liturgi Kudus
Konstitusi Liturgi KV II (Sacrosantum Concilium, SC) dalam kalimat pembukaan jelas mengatakan bahwa tujuan pembaharuan liturgi dalam semangat KV II adalah “ membuat cita rasa umat Kristiani dalam hidup keagamaannya semakin dalam, mencoba membaharui sesuai dengan tuntutan jaman hal yang memang perlu diubah sesuai dengan tuntutan jaman, membuat umat Kristiani semakin bersatu dan mencoba melakukan apa saja yang bisa membuat semakin banyak orang dipanggil dalam Gereja kudus” (SC 1).
Dengan demikian, ada tiga catatan penting sebelum memasuki persoalan pembaharuan liturgi. Pertama, tujuan pembaharuan liturgi supaya umat bisa semakin dalam menghayati hidup imannya. Kedua, diakui ada hal yang bisa diubah, yang bukan esensial namun terikat jaman sehingga perlu disesuaikan dengan cara pikir, ungkapan dan semangat hidup manusia dari jaman ke jaman. Liturgi bukan barang mati. Ada ungkapan luar (baca: bentuk) yang terikat pada jaman tertentu. Ekaristi yang kita punya sekarang pun mulai dengan tradisi Berkah Hamazod Paskah Yahudi dan awalnya tidak seperti sekarang bentuknya. Ekaristi yang kita kenal pun adalah Ritus Latin. Masih ada ritus lain seperti Ritus Yohanes Kristosmus dan Ritus Basilius Agung yang sering dipakai oleh Gereja Ortodoks. Dalam Gereja Latin pun disepakati ada ritus lain misalnya Ritus Ambrosius di Milan. Ketiga, tujuan misi yaitu membawa orang sebanyak mungkin ke dalam Gereja karena pembaharuan liturginya. Maka kelihatan jelas tujuan utama pembaharuan liturgi yang bukan asal dibaharui.
Mungkin kita akan bertanya, bagaimana caranya ketiga tujuan ini tercapai? Harus diingat bahwa misteri penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dikerjakan dalam simbol (tanda). Inilah arti sakramen. Sakramen (bagian dari liturgi kudus) adalah tanda yang mendatangkan rahmat. Kita tidak punya akses langsung dengan misteri, tetapi melalui pengantaraan (bahasa inggris yang tepat mediacy). Pengantaraan tersebut adalah melalui simbol atau tanda. Namun tanda ini bukan tanda kosong tanpa isi. Tanda dan yang ditandakan (baca: misteri Tuhan dan keselamatan-Nya) adalah satu meski tidak sama. Air bukanlah rahmat baptisan. Air tetap air. Tetapi Sakramen Baptis yang memakai air menjadi tanda bahwa terjadi perubahan (rahmat baptisan). Maka SC mengatakan yang membaptis adalah Kristus melalui imam-Nya, yang memberi sakramen adalah Kristus melalui imam-Nya (SC 7). Tetapi karena misteri penyelamatan dan Tuhan dinyatakan dalam bentuk upacara (baca: liturgi) yang penuh simbol maka tidak segera langsung dimengerti. Kita menghadapi “pengantara” via simbol. Maka yang terpenting adalah katekese atau pengajaran supaya umat yang mengikuti sadar dan tahu. Itulah sebabnya semangat pembaharuan liturgi KV II mengarah ke situ: kesadaran dan pengetahuan umat sehingga sadar dan tahu apa yang dirayakan (SC 11). Mengapa harus “sadar dan tahu?” SC mengatakan dengan sadar dan tahu umat akan partisipasi aktif dan lebih mantap dan banyak (efficacy) menikmati hasilnya. Dalam evaluasi sebelum KV II, Gereja melihat umat lebih sebagai penonton dalam banyak hal, tidak mengerti dan bahkan menganggap liturgi sebagai “magic,” sehingga yang terjadi ekses bahwa orang cuma hadir dan tidak menyadari apa yang dialami dan dirayakan. Itulah sebabnya “sadar dan tahu” sangat penting untuk berperanan aktif.
Sebagai imam, penulis memiliki contoh pengalaman. Ketika imam mengucapkan Doa Syukur Agung (DSA), yang hanya boleh diucapkan dan didoakan oleh imam sebagai wakil Kristus secara pribadi sebagai kepala (In personae Christi Caput), apakah umat sadar dan mengikuti? Apakah umat mengikuti doa yang panjang itu (apalagi DSA III/IV)? Kadangkala terlihat umat main HP atau diam saja tanpa mencermati kata demi kata DSA yang sebenarnya sangatlah inti dari Ekaristi. Tentu tidak semua umat. Tetapi, kalau ada survei atau jajak pendapat, mungkin mayoritas umat tidak mengerti dan mengikuti DSA, padahal isinya indah. Sekali lagi, “sadar dan tahu” akan membuat umat terlibat dan mendapatkan hasil yang matang. Mungkin kita lupa, yang merayakan Misa bukan hanya imam tetapi umat Allah dengan Kepalanya yaitu Kristus yang hadir dalam diri imam-Nya sebagai pemimpin upacara (presider).
Di sinilah kita berbicara mengenai pembaharuan dengan memakai bahasa lokal atau bahasa ibu (vernacular). SC mengatakan, dalam Ritus Latin (Roma) bahasa liturgi yang dipakai adalah Latin (SC 36 par. 1). Di situ dikatakan, meski dibolehkan bahasa ibu, tetap harus ada usaha untuk mempertahankan (preserve) pemakaian bahasa Latin. Namun “sadar dan tahu” serta partisipasi umat merupakan kriteria utama dalam berliturgi dan pembaharuan liturgi (SC 14). SC 14 juga mengatakan bahwa partisipasi aktif karena “sadar dan tahu” merupakan pelaksanaan imamat umum semua kaum beriman: bersama dengan imam yang merupakan wakil Kristus sebagai Kepala mereka mempersembahkan Ekaristi dan sakramen sebagai satu komunitas. Maka pemakaian bahasa ibu bukan hanya sekedar terjemahan melainkan pelaksanaan imamat umum kaum beriman.
Itulah sebabnya, sesuai SC 36 ayat 2, KV II mengijinkan pemakaian bahasa ibu dan memperluasnya dalam banyak upacara liturgi lainnya atas ijin dan pengesahan otoritas lokal yang tidak lain adalah Uskup setempat (SC 36 ayat 3). Maka KV II bukan hanya mengijinkan tetapi membiarkan keputusan Uskup lokal untuk memperluasnya dalam banyak liturgi atau upacara lainnya. Permasalahannya sekarang bukanlah mana yang sah atau tidak sah atau yang pantas atau tidak pantas, melainkan sejauh mana berguna untuk umat dalam melaksanakan imamat umumnya (SC 11).
Yang menarik adalah pernyataan KV II dalam SC yang mengatakan bahwa Gereja Katolik tidaklah bermaksud menyamaratakan. SC 37 mengatakan: “Gereja tak bermaksud memaksakan penyamarataan (uniformitas) kaku yang tidak berguna bagi iman umat dan komunitas; sebaliknya Gereja menghormati dan mendorong usaha kreatif dan asli serta talenta (dalam berliturgi tentunya, penjelasan penulis) dari berbagai ras dan bangsa. Segala hal yang tidak berbau berhala dan tahyul akan dipelajari Gereja dengan teliti dan akan dikembangkan kalau memang tidak bersifat tahyul dan berhala serta berguna bagi perkembangan dan penghayatan iman umat. Bahkan kadangkala dimasukkan unsur-unsur (budaya manusia, penjelasan penulis) ke dalam liturgi Gereja selama sesuai dengan maksud dan tujuan liturgi Gereja (SC 37). Ini tentu menarik karena kita berpikir bahwa inovasi yang benar ditolak Gereja. Di sinilah dibutuhkanstudi yang serius dari segi sejarah, teologi, pastoral, spitualitas dan aspek hukum Gereja (SC 16). Kata kunci di sini adalah “studi yang serius.” Maka pertanyaannya bukanlah boleh atau tidak memakai bahasa lokal atau memasukkan unsur budaya masyarakat, melainkan “apakah ada studi yang serius sesuai amanat SC 16 atau tidak?” Sekali lagi: permasalahannya adalah demi kemajuan iman dan penghayatan umat, dan tentu yang lebih mendalam pelaksanaan imamat umum kaum beriman, sehingga membawakan hasil rohani yang dalam bagi umat sebagai kriteria utama.
Di sinilah kita melihat, pendapat bahwa seolah-olah penggunaan bahasa lokal dan inkulturasi dianggap salah dan menyimpang adalah jauh dari semangat KV II. Jauh dari anggapan salah. Bahkan KV II memberikan keleluasaan dan dorongan dengan tujuan pelaksanaan imamat umum kaum beriman terlaksana dan mendatangkan buah rohani.
Adalah pengingkaran semangat dan isi KV II kalau kita berbicara atau menolak penggunaan bahasa lokal dalam liturgi. Gereja Katolik sangat terbuka dan fleksibel sejauh praktek liturgi dilakukan dalam semangat dan substansi (isi) KV II. Kesalahan dan ekses kadangkala akibat tidak mengerti, terlalu bersemangat dan kurang studi yang serius. Tetapi mengatakan penggunaan unsur lokal bertentangan dengan Gereja justru adalah kesalahan dan penolakan terhadap KV II yang bersifat tidak dapat sesat (infalibilitas). KV II malah maju dengan memasukkan kategori “daerah misi.”
Dalam SC 38 dikatakan: “Ketentuan mesti dibuat ketika kita merevisi (membaharui) buku-buku liturgi, demi alasan yang dapat dibenarkan dan penyesuaian dengan kelompok-kelompok, daerah-daerah dan bangsa-bangsa berbeda, terutama di daerah misi, dengan menjunjung tinggi kesatuan Ritus Roma dalam hakekat dan isinya…” Maka kelihatan Gereja sangat terbuka dan bertujuan misioner. Di sinilah terlihat keterbukaan Gereja sebagai Ibu yang merangkul semua orang dan mau semua orang diselamatkan (1 Tim 2: 4). Semua itu dilakukan Gereja karena melihat bahwa rahmat Tuhan tidak boleh dibatasi oleh manusia secara picik. Kesatuan iman itu adalah rohani pada intinya dan bukan hanya soal ungkapan luar. Ungkapan luar hanya berarti kalau melayani tujuan rohani dan bukan sebaliknya. Ungkapan luar penting sejauh berguna bagi tujuan dan misi Gereja dan bukan sebaliknya.
Itulah sebabnya Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI berkali-kali mengatakan KV II adalah karya Roh Kudus untuk Gereja di masa modern. Ini bukan sekedar ucapan di bibir tapi terlihat dari kebijaksanaan Gereja dalam isi dokumennya. Maka mengingkari dan mencoba menafsirkan sendiri bisa jadi karena tidak mengerti dan menguasai isi dan semangat KV II dan mencuplik hanya sebagian teks sesuai keinginan sendiri. Apalagi dokumen itu tidak ditafsirkan dari sisi sejarah, pastoral, spiritual, teologi dan hukum yang benar. Penulis mengerti, KV II baru berusia 50 tahun. Perlu banyak waktu untuk dipelajari dan direnungkan. Maka peringatan 50 tahun KV II adalah usaha yang bagus untuk mempelajari dengan serius dan benar.
Ada usaha untuk kembali kepada liturgi Pius V (Trente) baik tata cara maupun penggunaan bahasa Latin. Gereja Katolik tidak pernah menolak atau menghapuskan ritus Pius V. Segala ritus yang ada tetap sah, meski demi kesatuan Gereja universal tidak digunakan. Penggunaan kembali Ritus Pius V adalah usaha genius Paus Benediktus XVI untuk rekonsiliasi (persatuan kembali dalam perdamaian dan kasih) dengan kelompok Lefvebre yang menolak hasil KV II. Paus Benediktus XVI bermurah hati dengan mengakomodasi tuntutan mereka, termasuk Misa Ritus Pius V. Sebenarnya ini bukan pengecualian karena ritus yang ada tidak pernah ditolak (SC 4). Maka usaha Benediktus XVI bukan tanpa dasar melainkan justru ada dalam KV II: Ritus Pius V tidak pernah dihapuskan sama sekali! Salah juga mengatakan Ritus Pius V (Trente) sudah dihapus dengan Ritus Roma Paus Paulus VI. Permasalahannya bukan valid atau tidak valid, sah atau tidak sah. Permasalahannya, konteks Benediktus XVI adalah demi kesatuan kembali Gereja, terutama kelompok Lefevbre. Maka yang diutamakan di sini adalah kesatuan Gereja. Maka apabila tidak ada masalah dengan kesatuan Gereja, yang terjadi karena penolakan hasil KV II (misalnya Kelompok Lefevbre), tidaklah pada tempatnya kalau justru meminta Misa Ritus Pius V dengan alasan lebih sakral daripada Misa Ritus Paus Paulus VI.
Penggunaan ritus Pius V harus dilihat sebagai “luar biasa” (extra-ordinary) (sesuai maksud dokumen yang diundangkan oleh Benediktus XVI) dalam liturgi Gereja dan bukan hal yang umum. Kalau dalam keadaan biasa, demi kesatuan Gereja hendaknya dipakai ritus Paus Paulus VI. Maka persoalannya adalah kesatuan Gereja yang tidak lain adalah cinta kasih. Cinta kasih mempersatukan dan bukan membuat perbedaan (apalagi asal beda dan menolak yang umum dengan alasan bahwa yang sekarang kurang baik dan tepat) sehingga muncul pertentangan. Persoalannya bukan sah atau tidak, apalagi lebih baik atau kurang baik, melainkan demi cinta kasih yang mempersatukan. Demi kesatuan ritus hendaknya di dalam keadaan normal (tidak ada masalah dengan kelompok yang dari awal sudah bermasalah dengan hasil KV II) pemakaian Misa Ritus Paus Paulus VI adalah normal dan umum berlaku (ordinary).
Penggunaan Ritus Pius V adalah lain dengan menggunakan bahasa Latin dalam misa Ritus Paus Paulus VI hasil KV II. Bahasa apapun tetap bisa dipakai, apalagi sesuai amanat SC, bahasa Latin hendaknya dipertahankan sebagai khazanah tradisi karena kita adalah Ritus Latin (Roma). Dalam perayaan besar, penulis sendiri kadangkala menggunakan bahasa Latin. Namun, “menggunakan bahasa Latin” berbeda dengan mengatakan “hanya Misa dalam bahasa Latin yang benar, baik dan apalagi yang paling sah.” Pendapat ini sama saja mengatakan pemakaian bahwa bahasa lokal dilarang oleh KV II. Padahal, KV II bukan hanya tidak melarang, melainkan memberikan fleksibilitas yang tinggi pemakaiannya secara umum (publik). Hendaknya pembimbing rohani dan umat mempelajari isi dan semangat dokumen KV II dengan teliti dan mendalam sesuai makna peringatan 50 tahun KV II.***
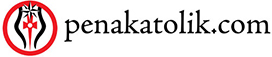







[…] merupakan tanggapan terhadap artikel yang ditulis Rm. Johanes Robini Marianto, OP, yang berjudul Semangat Pembaharuan Liturgi Konsili Vatikan II. Rm Robini membahas berbagai hal seputar Konsili Vatikan II, secara khusus tentang pembaharuan […]